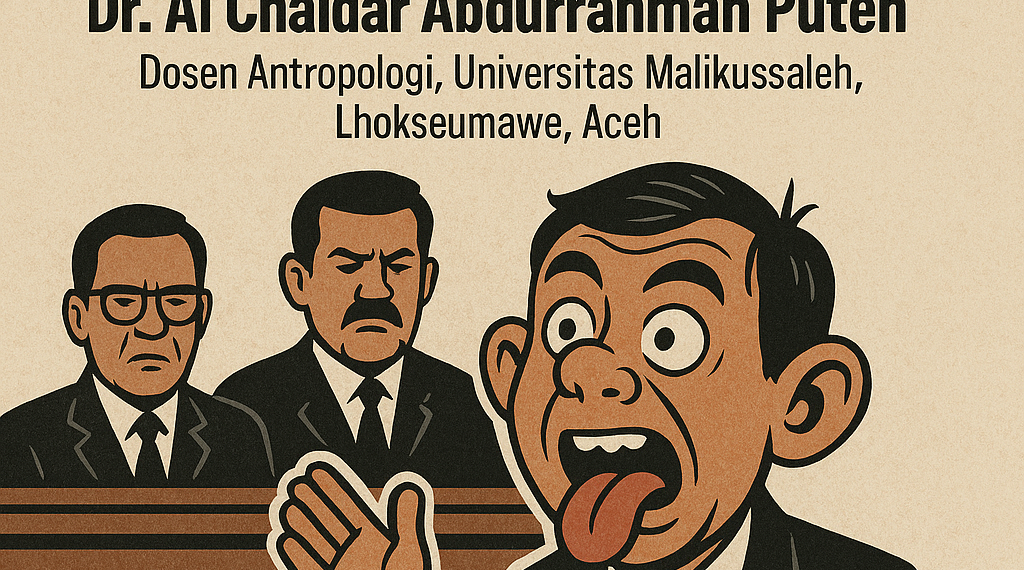Dengarkan Artikel
Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh
Dosen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Nabi Muhammad SAW menggambarkan masa penuh tipu daya, sanawat khaddaa’at, di mana pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap berdusta, pengkhianat dipercaya, dan orang amanah justru dicap pengkhianat. Di tengah kekacauan nilai itu, muncul sosok yang disebut ruwaibidah: orang hina, kecil, atau bodoh yang tiba-tiba mengurusi urusan publik. Hadis ini bukan sekadar nubuat, melainkan peringatan tentang bagaimana masyarakat bisa terjerumus ketika standar kepemimpinan runtuh.
Nabi Muhammad SAW pernah menyebut akan datang masa penuh tipu daya, sanawat khaddaa’at, di mana pendusta dianggap jujur, orang jujur dianggap dusta, pengkhianat dipercaya, dan orang amanah dicap pengkhianat. Di masa itu, urusan publik justru diatur oleh ruwaibidah—orang hina dan bodoh yang tiba-tiba tampil sebagai penguasa. Tragedi banjir dan longsor Sumatra 2025 seolah menjadi panggung nyata dari nubuat itu.
Fenomena yang digambarkan hadis tersebut terasa akrab dalam politik kontemporer. Kita menyaksikan pemimpin yang tidak kompeten, namun tetap berkuasa berkat propaganda dan manipulasi. Korupsi dilembagakan, pengkhianatan terhadap rakyat dianggap strategi, dan kejujuran dipinggirkan sebagai kelemahan. Bahkan bencana lingkungan—banjir, kebakaran hutan, ekosida yang merenggut nyawa—sering kali lahir dari keputusan rezim yang lebih peduli pada rente ekonomi ketimbang amanah publik. Ruwaibidah hari ini tidak lagi tampil sebagai sosok hina yang jelas terlihat, melainkan sebagai figur yang berpenampilan rapi, berbicara dengan jargon modern, namun tetap mengelola negara dengan kebodohan dan tipu daya.
Dekolonial dan Islamic Studies: Membongkar Tipu Daya
Kerangka dekolonial menawarkan cara membaca ulang fenomena ini. Ia mengingatkan bahwa banyak sistem politik dan epistemologi yang kita warisi adalah produk kolonialisme, yang menyingkirkan nilai amanah dan keadilan demi kepentingan kekuasaan. Islamic studies, di sisi lain, menyediakan etika normatif yang menekankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai fondasi kepemimpinan. Ketika keduanya dipadukan, kita memperoleh alat analisis yang tajam: melihat bagaimana rezim kontemporer beroperasi sebagai ruwaibidah modern, sekaligus merumuskan alternatif berbasis nilai keadilan dan amanah.
Ironi terbesar dari rezim Ruwaibidah adalah bahwa masyarakat sering kali ikut menormalisasi kebohongan. Pendusta dielu-elukan sebagai komunikator ulung, pengkhianat dipuja sebagai pragmatis, dan orang jujur dicap naif. Inilah tragedi politik yang terus berulang: rakyat yang seharusnya menjadi subjek sejarah justru dijadikan objek tipu daya. Hadis Ruwaibidah, jika dibaca dengan serius, bukan sekadar peringatan spiritual, melainkan kritik sosial yang relevan lintas zaman.
📚 Artikel Terkait
Judul artikel ini “Ketika Orang Bodoh Jadi Ahli Negara” bukan sekadar ejekan, melainkan refleksi atas kenyataan pahit. Kita hidup di era di mana kebodohan bisa dilembagakan, dan tipu daya bisa dijadikan strategi politik. Namun, dengan membaca ulang hadis Ruwaibidah melalui lensa dekolonial dan etika Islam, kita diajak untuk tidak sekadar mengeluh, melainkan merumuskan jalan keluar: membongkar epistemologi kolonial, mengembalikan amanah sebagai nilai dasar, dan menolak normalisasi kebohongan. Karena jika tidak, kita hanya akan terus menjadi penonton dalam panggung sarkasme politik yang tak pernah usai.
Bencana yang Mencekam di Medsos
Ketua BNPB menyebut bencana alam di Aceh “hanya mencekam di media sosial.” Pernyataan ini ironis: seakan-akan ribuan korban hanyalah trending topic, bukan kenyataan pahit. Dalam logika ruwaibidah, penderitaan rakyat bisa direduksi menjadi sekadar citra digital, bukan fakta yang menuntut tanggung jawab.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan bangga menyatakan bahwa listrik di Aceh sudah hidup 90 persen. Angka itu terdengar meyakinkan, tetapi menutupi kenyataan bahwa banjir bandang dan longsor terjadi akibat kerusakan lingkungan yang dibiarkan selama bertahun-tahun. Inilah gaya khas rezim Ruwaibidah: menyalakan lampu sambil memadamkan hutan.
Bantuan Malaysia “Tidak Seberapa”
Mendagri menilai bantuan Malaysia hanya Rp1 miliar dan menyebutnya “tidak seberapa.” Pernyataan ini bukan sekadar angka, melainkan cermin arogansi. Solidaritas internasional diremehkan, sementara negara sendiri gagal menyediakan perlindungan yang layak. Ruwaibidah memang pandai menghitung, tapi hanya untuk merendahkan, bukan untuk membangun.
Karung Beras dan Jejak Izin Hutan
Zulkifli Hasan tampil heroik membawa karung beras untuk korban banjir bandang. Namun publik tak lupa bahwa kebijakan kehutanan masa lalunya memberi izin pembukaan hutan yang memperparah kerusakan lingkungan. Gestur karung beras itu menjadi simbol ironis: menolong korban dari bencana yang lahir dari kebijakan tangan sendiri. Ruwaibidah bukan hanya bodoh, tapi juga piawai berakting.
Tragedi Sumatra 2025 memperlihatkan bagaimana rezim Ruwaibidah bekerja: penderitaan rakyat dijadikan panggung citra, angka dipakai untuk menutupi kerusakan, solidaritas diremehkan, dan karung beras dijadikan alat pencitraan. Hadis Ruwaibidah bukan sekadar nubuat, melainkan kritik sosial yang hidup. Ironinya, kita menyaksikan bagaimana tipu daya dilembagakan, sementara rakyat dibiarkan hanyut bersama lumpur dan banjir.

POTRET Gallery
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini