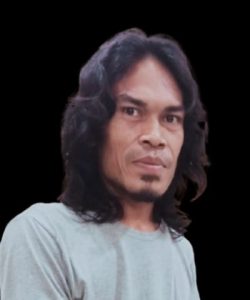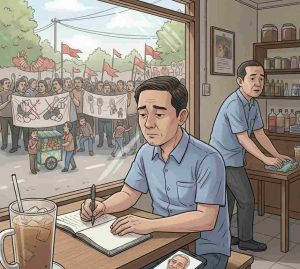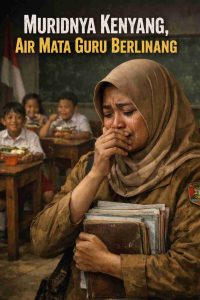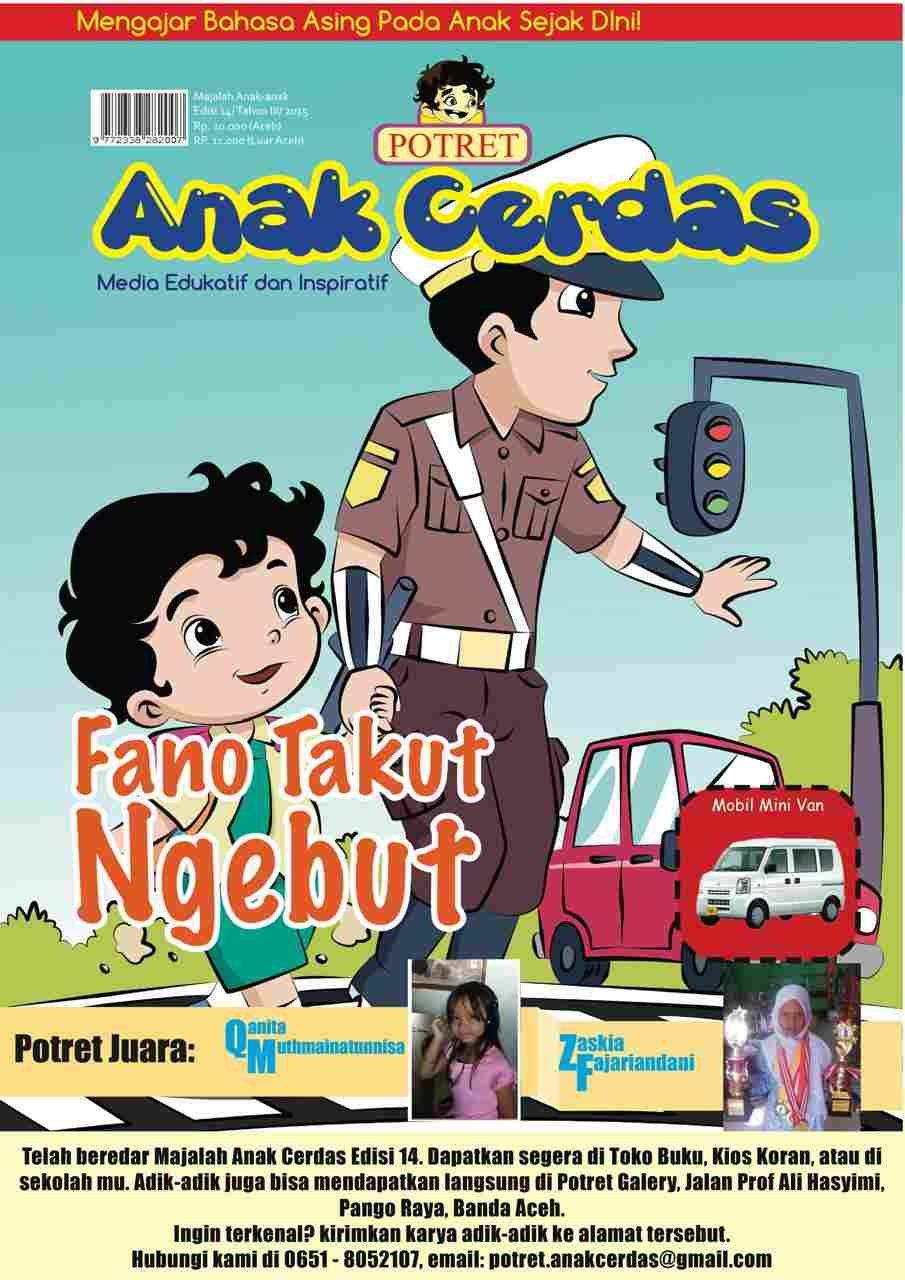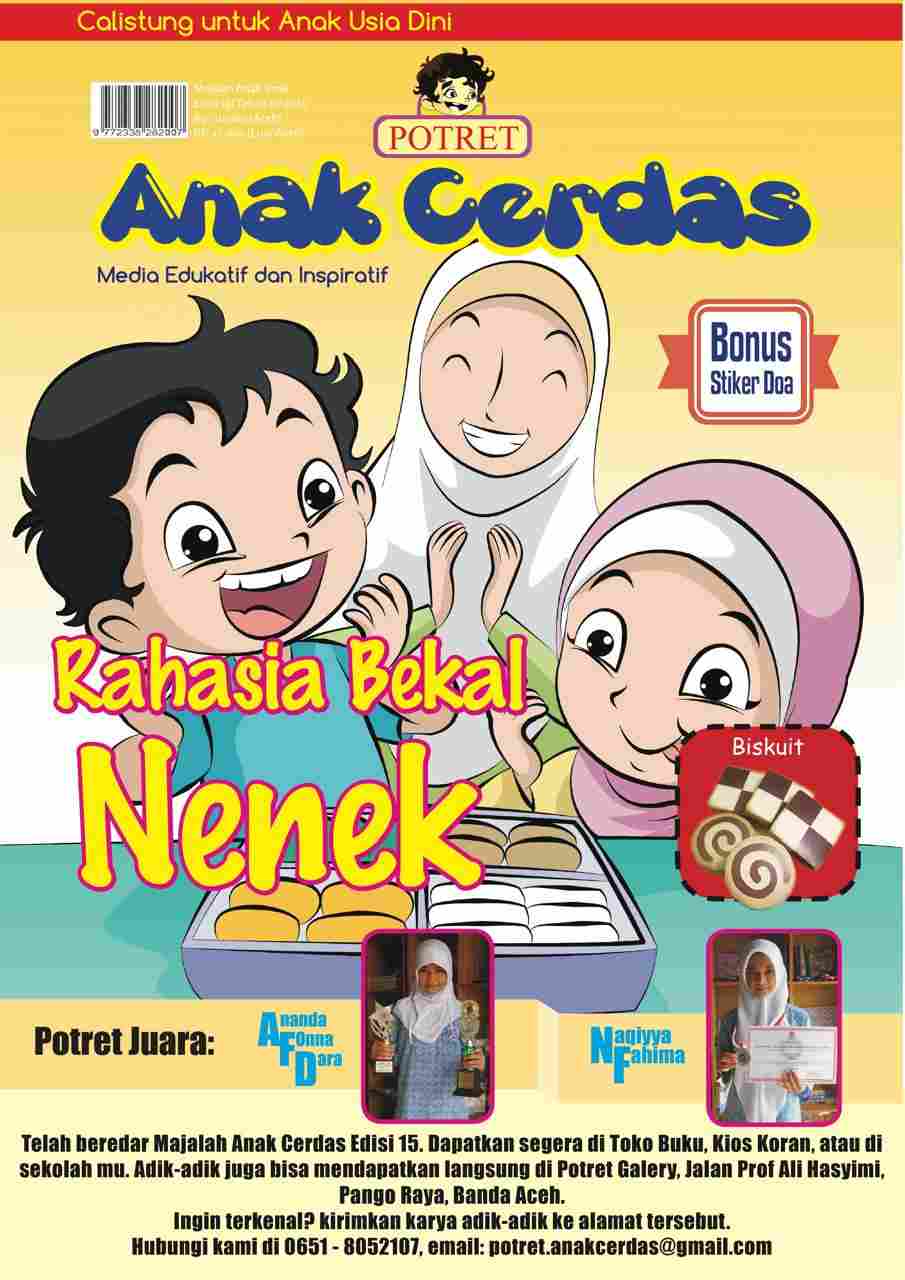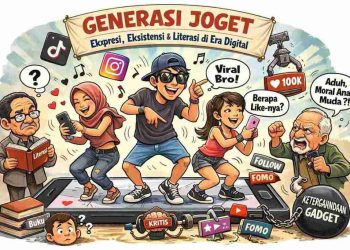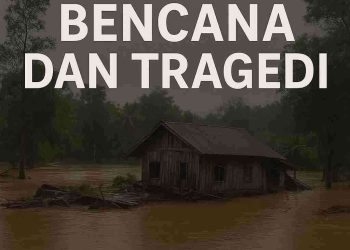Dengarkan Artikel
Oleh Dayan Abdurrahman
- Dunia yang Berubah, Manusia yang Tertinggal
Dunia hari ini bergerak lebih cepat dari sistem pendidikan kita. Di tengah revolusi digital dan otomatisasi industri, manusia kini dinilai bukan dari gelar yang tertera di kertas, tetapi dari real skill — kemampuan nyata yang dapat memecahkan masalah, mencipta solusi, dan memberi nilai bagi masyarakat. Namun ironisnya, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sistem pendidikan masih sibuk menilai nilai ujian dan akreditasi, bukan kemampuan berpikir, bekerja sama, dan berinovasi.
Berdasarkan data UNESCO (2023), hanya 37% lulusan perguruan tinggi di Asia Tenggara yang memiliki kompetensi kerja sesuai kebutuhan industri. Di Indonesia sendiri, lebih dari 60% perusahaan mengaku kesulitan mencari tenaga kerja yang benar-benar siap kerja (World Bank, 2022). Artinya, kita sedang mencetak lebih banyak pemegang ijazah daripada pemecah masalah.
- Gelar Tak Lagi Menjadi Jaminan
Di banyak negara maju, seperti Jerman, Finlandia, dan Korea Selatan, gelar akademik tidak lagi menjadi ukuran utama. Mereka membangun sistem pendidikan berbasis dual system, di mana pelajar tidak hanya belajar teori di kelas tetapi juga magang langsung di industri. Misalnya, di Jerman, sekitar 52% siswa SMA memilih jalur vokasional yang terhubung langsung dengan dunia kerja. Hasilnya? Tingkat pengangguran muda mereka hanya 5,4%, jauh di bawah rata-rata global (ILO, 2022).
Sebaliknya, di Indonesia, tingkat pengangguran sarjana justru meningkat menjadi 6,2% pada 2023, lebih tinggi dari lulusan SMA (BPS). Fenomena ini menunjukkan paradoks: semakin tinggi pendidikan formal seseorang, belum tentu semakin tinggi pula kemampuan praktisnya. Banyak mahasiswa menghabiskan waktu mengejar gelar, bukan keterampilan.
- Kearifan Lokal dan Realitas Sosial Aceh
Aceh memiliki akar pendidikan Islam yang kuat dan budaya belajar yang luhur. Di masa lalu, dayah menjadi pusat ilmu dan keterampilan sosial. Ulama bukan hanya mengajar kitab, tapi juga mengajarkan hikmah hidup — bagaimana manusia menjadi berguna bagi lingkungan. Namun modernisasi pendidikan telah menggeser nilai itu. Kita mulai mengukur kesuksesan dari ijazah, bukan manfaat.
Padahal, masyarakat Aceh memiliki filosofi: “ilmu keu pang, amal keu nyang” — ilmu harus disertai amal nyata. Spirit ini sejalan dengan semangat skill-based education yang kini diterapkan di negara maju. Di Jepang misalnya, pelajar SD sudah diajarkan life skills: cara bekerja sama, menjaga kebersihan, dan menghormati waktu. Hasilnya terlihat nyata — masyarakat disiplin, produktif, dan rendah konflik sosial.
Aceh bisa menghidupkan kembali semangat itu: membangun sistem pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai lokal tapi berorientasi global — di mana iman dan skill berjalan seimbang.
- Data Sosial dan Tantangan Nyata
Menurut survei Katadata Insight (2024), hanya 29% mahasiswa Indonesia yang merasa kuliahnya relevan dengan pekerjaan yang mereka jalani. Sementara itu, 41% perusahaan menyatakan bahwa lulusan baru belum memiliki soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu.
📚 Artikel Terkait
Kondisi ini diperparah oleh kebijakan birokratis yang masih mengutamakan gelar untuk promosi jabatan. Padahal, negara-negara seperti Singapura telah menghapus syarat ijazah untuk sebagian besar posisi di sektor publik sejak 2021. Pemerintah di sana lebih menilai portfolio of experience dan hasil kerja.
Indonesia masih perlu waktu untuk sampai ke tahap itu, tetapi langkah awalnya adalah reorientasi pendidikan: dari berorientasi pada dokumen ke berorientasi pada kemampuan.
- Perspektif Global dan Pembelajaran dari Dunia Nyata
Kita hidup di masa ketika Google, Apple, IBM, dan Tesla sudah tidak lagi mensyaratkan gelar sarjana untuk melamar kerja. Mereka mencari orang dengan problem-solving mindset dan creative execution. Bahkan, laporan LinkedIn (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 70% rekruter global kini lebih menilai skill portfolio daripada pendidikan formal.
Sementara itu, di Finlandia, teacher training difokuskan pada kemampuan mendidik anak berpikir kritis dan adaptif. Hasilnya, negara itu menjadi salah satu dengan sistem pendidikan terbaik dunia tanpa ujian nasional yang kaku. Di Korea Selatan, pendidikan vokasi diformulasikan bersama industri kreatif dan teknologi, menghasilkan tenaga muda yang siap kerja dan inovatif.
Bandingkan dengan realita kita: pelajar seringkali terjebak dalam hafalan, bukan analisa; mengejar nilai, bukan makna. Padahal, dunia kerja tidak menanyakan nilai IPK, tapi bagaimana seseorang menyelesaikan masalah nyata di lapangan.
- Pembaharuan: Dari Kelas ke Kehidupan
Sudah saatnya pendidikan tidak hanya mengajarkan pelajaran, tetapi menghidupkan pelajaran. Dunia tidak butuh lebih banyak lulusan yang pandai bicara teori tapi bingung ketika dihadapkan pada kenyataan. Kita butuh generasi yang hands-on, yang belajar dari lapangan, dari masyarakat, dari alam.
Sebagaimana Aceh kaya dengan sumber daya alam dan budaya kerja gotong royong, pembelajaran berbasis proyek sosial dan alam bisa menjadi fondasi pendidikan masa depan. Mahasiswa pertanian, misalnya, seharusnya tidak hanya menulis skripsi, tetapi juga menciptakan model tanam yang efisien di lahan kering Aceh. Mahasiswa ekonomi harus mampu memecahkan persoalan UMKM lokal, bukan sekadar mempresentasikan teori pasar.
- Menuju Pendidikan yang Membebaskan
Kita harus berani menepi dari kebanggaan lama — bahwa gelar adalah simbol harga diri. Paradigma baru harus menempatkan manusia sebagai pembelajar sejati (lifelong learner), bukan pemburu ijazah. Pendidikan tidak boleh berhenti di ruang kelas, tapi harus menjadi jalan hidup yang membangun nilai, bukan hanya nama.
Dengan demikian, masa depan pendidikan bukan lagi gelar akademik di dinding, tapi kompetensi di tangan dan karakter di dada.
Sebagaimana kata bijak Aceh, “Lôn hana keu ureueng meu ilmeu, keu ureueng meu akal nyan ban mandum ilmeu” — orang berakal, dialah yang sejatinya berilmu.
- Penutup
Jika negara ingin maju, ia harus mengubah cara menilai manusia. Gelar boleh tetap penting, tapi bukan satu-satunya ukuran. Dunia kerja, masyarakat, dan masa depan menuntut sesuatu yang lebih nyata — kemampuan, kejujuran, kreativitas, dan kepedulian sosial.
Pendidikan sejati bukanlah tentang mencetak manusia untuk bekerja, tapi membangun manusia untuk berkarya. Dunia tidak menunggu mereka yang berijazah, tetapi mereka yang berdaya, berkarya, dan berkontribusi nyata.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini