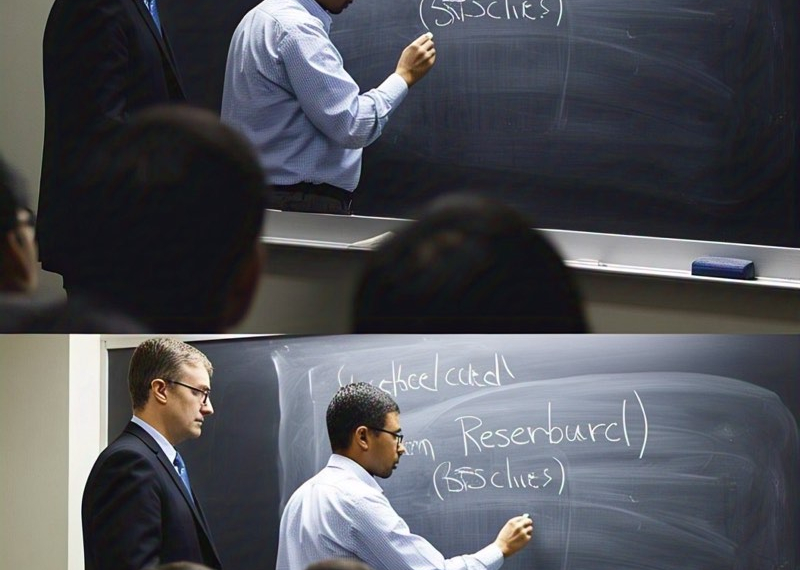Dengarkan Artikel
(Dari Sekadar Mengajar Menuju Tradisi Publikasi)
Oleh Dayan Abdurrahman
Di era digital yang serba cepat dan kompetitif ini, akademisi dituntut untuk tak hanya mengajar, tetapi juga menciptakan pengetahuan baru melalui publikasi ilmiah. Publikasi bukan sekadar formalitas untuk naik jabatan, melainkan bagian integral dari integritas keilmuan seorang dosen dan peneliti. Ia adalah medium untuk mengabarkan hasil penelitian kepada komunitas ilmiah global, serta menjadi tolak ukur reputasi suatu institusi pendidikan tinggi.
Namun demikian, di Indonesia, tradisi publikasi ilmiah masih menghadapi banyak tantangan, meski peluang untuk maju sebenarnya terbuka lebar berkat kemajuan teknologi digital.
Secara umum, jumlah publikasi Indonesia dalam indeks internasional seperti Scopus terus meningkat. Data Scopus 2023 menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 34.000 publikasi dalam setahun. Meski angka ini patut diapresiasi, secara rasio terhadap jumlah penduduk dan dosen, produktivitas kita masih tertinggal.
Jika dihitung per satu juta penduduk, Indonesia baru mencapai 122 publikasi, jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia (1.363), apalagi Singapura yang mencetak lebih dari 10.000 publikasi per satu juta penduduk. Negara-negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, dan bahkan Israel yang hanya memiliki sekitar 9 juta penduduk, mampu menghasilkan puluhan ribu karya ilmiah berkualitas tiap tahun.
Perbedaan mencolok ini disebabkan oleh ekosistem riset dan kebijakan publikasi yang sangat berpihak pada kualitas dan keberlanjutan. Di Malaysia, publikasi ilmiah menjadi prasyarat utama untuk promosi akademik, didukung oleh insentif pemerintah dan lembaga riset.
Di Singapura dan Israel, kolaborasi internasional menjadi tulang punggung strategi pengembangan riset—dosen dan peneliti tidak hanya bekerja di laboratorium, tetapi juga aktif menjalin jejaring riset global. Di Inggris dan Amerika, budaya menulis dan berpikir kritis telah ditanamkan sejak dini, bahkan pada tingkat sarjana.
Data menunjukkan kolaborasi internasional publikasi di Inggris mencapai 55%, Singapura 46%, dan Israel 50%, sedangkan Indonesia baru sekitar 8%. Angka ini mengindikasikan pentingnya membangun jejaring dan membuka ruang sinergi lintas negara.
Sementara itu, akademisi di Indonesia kerap terjebak dalam rutinitas administratif yang menyita energi. Banyak dosen menghabiskan waktunya untuk laporan akreditasi, sistem informasi akademik, dan pengajaran yang padat, tanpa ruang cukup untuk berpikir, meneliti, dan menulis.
Kemampuan menulis akademik dalam bahasa Inggris pun masih menjadi kendala utama. Belum semua perguruan tinggi memiliki pusat pelatihan penulisan ilmiah yang aktif, dan akses ke jurnal-jurnal bereputasi internasional masih terbatas di banyak daerah. Lebih dari itu, budaya publikasi kita sering kali dibentuk oleh motif kewajiban—bukan karena kebutuhan intelektual. Tak heran, praktik publikasi di jurnal predator pun masih marak terjadi.
📚 Artikel Terkait
Namun, kita tak boleh hanya berkutat pada tantangan. Era digital sebenarnya menghadirkan peluang emas yang belum pernah dimiliki oleh generasi akademisi sebelumnya. Kini, semakin banyak jurnal ilmiah bereputasi membuka akses terbuka (open access), bahkan menerima kontribusi dari negara berkembang.
Beragam platform seperti ResearchGate, ORCID, dan Academia.edu memberikan ruang interaksi global tanpa sekat geografis. Alat bantu penulisan seperti Grammarly, Quillbot, dan ChatGPT memungkinkan penyusunan draft awal, penyuntingan struktur, bahkan pendalaman ide secara lebih efisien. Pelatihan daring (webinar) mengenai teknik publikasi internasional kini tersedia luas dan sering kali gratis, diselenggarakan oleh lembaga luar negeri yang dapat diakses dari mana saja.
Peluang ini hanya akan bermakna bila diikuti dengan perubahan cara pandang dan sistem. Institusi pendidikan tinggi perlu mendorong perubahan budaya akademik dari dalam: menumbuhkan semangat riset sejak tingkat mahasiswa, mendorong penulisan tugas akhir yang berkualitas dan dapat diolah menjadi artikel ilmiah, serta menjadikan dosen senior sebagai mentor publikasi bagi dosen muda.
Insentif publikasi sebaiknya tidak hanya berbasis kuantitas, melainkan kualitas dan dampak. Dukungan nyata seperti dana riset, akses database ilmiah, dan bantuan editorial sangat krusial. Selain itu, penting untuk membentuk komunitas riset kolaboratif lintas fakultas, universitas, dan bahkan antarnegara.
Belajar dari negara-negara yang lebih unggul, Indonesia perlu segera memperkuat sistem meritokrasi berbasis publikasi. Di Israel, misalnya, hampir seluruh riset diarahkan pada kebutuhan nasional dan memiliki payung koordinatif antarlembaga, sehingga berdampak langsung pada inovasi dan ekonomi. Singapura menjadikan riset sebagai bagian dari strategi diplomasi akademik dan pembangunan nasional.
Inggris dan AS, melalui universitas riset kelas dunia, menekankan pentingnya sitasi dan dampak ilmiah, bukan sekadar jumlah publikasi. Transformasi ini juga harus menyentuh aspek integritas ilmiah. Di tengah tekanan untuk produktif, marak terjadi duplikasi data, manipulasi hasil riset, bahkan plagiarisme.
Ini menjadi ancaman serius terhadap kredibilitas ilmuwan kita di mata dunia. Maka penting bagi semua pihak—dari Kemendikbudristek, rektorat, hingga komunitas dosen—untuk menegakkan etika publikasi dan membangun kesadaran kolektif bahwa publikasi yang jujur dan berdampak jauh lebih bernilai daripada angka tinggi yang semu.
Di Mana Kita?
Secara kuantitatif, Indonesia memang menunjukkan tren meningkat dalam publikasi ilmiah. Berdasarkan data Scopus tahun 2023, Indonesia menghasilkan sekitar 34.000 dokumen ilmiah dalam setahun. Namun jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan dosen, angka itu belum menunjukkan rasio produktivitas yang optimal.
Lihat tabel berikut sebagai pembanding:
| Negara | Penduduk (juta) | Publikasi (Scopus 2023) | Publikasi per 1 juta penduduk | Kolaborasi Internasional (%) |
| Indonesia | 278 | ±34.000 | ±122 | 8% |
| Malaysia | 33 | ±45.000 | ±1.363 | 24% |
| Singapura | 5,9 | ±60.000 | ±10.169 | 46% |
| Inggris | 67 | ±170.000 | ±2.537 | 55% |
| AS | 331 | ±480.000 | ±1.450 | 38% |
| Israel | 9,3 | ±45.000 | ±4.839 | 50% |
Penutupnya, era digital bukanlah musuh bagi akademisi, tetapi jendela baru yang bisa membebaskan dari sekat-sekat lama. Kita perlu menyambutnya dengan kesiapan mental, sistem yang mendukung, dan budaya ilmiah yang kuat. Indonesia memiliki potensi besar dalam jumlah, tetapi potensi itu harus ditransformasikan menjadi kekuatan melalui kerja sistemik dan komitmen bersama.
Jika negara-negara kecil seperti Singapura dan Israel mampu menciptakan ekosistem publikasi yang unggul dengan sumber daya terbatas, maka tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tertinggal.
Menjadi akademisi hari ini bukan hanya soal berada di ruang kelas atau ruang sidang, melainkan juga hadir dalam percakapan global melalui publikasi. Inilah saatnya akademisi Indonesia menjadikan publikasi ilmiah sebagai bagian dari identitas keilmuannya, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan demikian, kontribusi kita sebagai insan akademik akan tercatat tidak hanya di lokalitas kampus, tetapi juga di peta pengetahuan dunia.
*Domisili Aceh Besar, Peminat Pendidikan Tinggi
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini