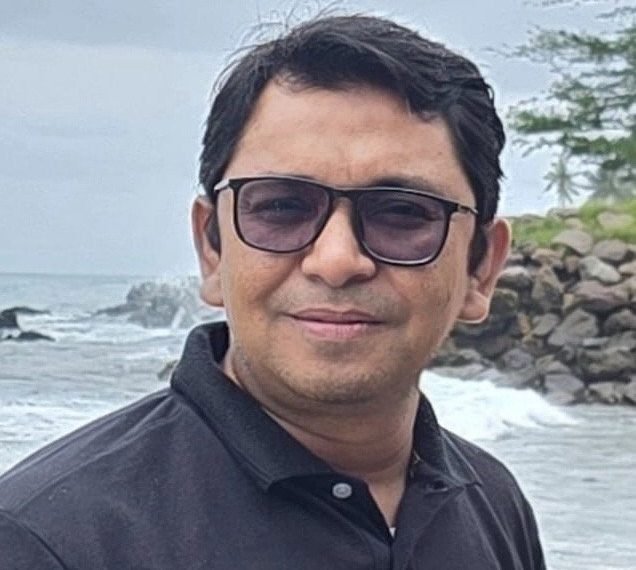Dengarkan Artikel
Oleh: Azharsyah Ibrahim
Dalam lanskap ekonomi masyarakat Aceh, khususnya di wilayah agraris seperti di banyak wilayah di Aceh, tanah bukan sekadar aset properti, melainkan instrumen vital bagi keberlangsungan hidup dan martabat sosial. Salah satu fenomena muamalah yang paling mengakar dalam kehidupan petani di daerah ini adalah praktik Gala Tanoh. Secara terminologi lokal, Gala Tanoh dipahami sama dengan gadai sawah, atau dalam istilah fiqh Islam dikenal sebagai Al-Rahnu.
Hasil kajian sejumlah peneliti termasuk penulis sendiri di sejumlah wilayah di Aceh menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik adat yang diwariskan secara turun-temurun dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang murni. Wilayah Aceh bagian utara dan timur, dengan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai petani, menjadi locus penelitian yang relevan untuk melihat bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan kebiasaan masyarakat dalam transaksi utang-piutang berbasis jaminan tanah.
Konsep Al-Rahnu dan Praktik Gala
Sebelum membedah praktik di lapangan, penting untuk memahami landasan teoretis Al-Rahnu. Secara bahasa, Al-Rahnu berarti tetap, kekal, atau penahanan. Dalam terminologi syara’, ia didefinisikan sebagai menjadikan barang yang bernilai harta sebagai jaminan utang, yang memungkinkan utang tersebut dibayar dengannya jika pihak yang berutang tidak sanggup melunasinya.
Landasan hukum gadai sangat kuat dalam Islam, merujuk pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 dan hadis Rasulullah SAW yang pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan. Para ulama sepakat bahwa akad gadai (rahn) hukumnya boleh, baik saat bermukim maupun dalam perjalanan.
Namun, titik krusial dalam gadai syariah terletak pada pemanfaatan barang gadai (marhun). Prinsip dasarnya adalah barang gadai dan manfaatnya tetap menjadi milik orang yang menggadaikan (rahin). Penerima gadai (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang tersebut kecuali seizin rahin, dan pemanfaatan itu pun hanya sekadar pengganti biaya pemeliharaan jika ada. Jika pemanfaatan dilakukan tanpa dasar yang haq, maka setiap utang yang menarik manfaat dianggap sebagai riba.
Masyarakat Aceh dikenal religius, dengan struktur sosial yang menghormati ulama dan memiliki fasilitas keagamaan yang memadai seperti masjid, meunasah, dan dayah. Namun, dalam aspek muamalah Gala Tanoh, tradisi sering kali berjalan di jalur yang berbeda dengan teori fiqh yang diajarkan.
Berdasarkan temuan lapangan, praktik Gala Tanoh biasanya terjadi ketika seseorang membutuhkan dana mendesak, seperti untuk biaya pengobatan, pesta pernikahan, atau kebutuhan konsumtif lainnya. Uniknya, transaksi ini jarang menggunakan uang tunai sebagai objek pinjaman. Masyarakat lebih memilih emas (dihitung dalam satuan mayam, 1 = 3,33 gram) sebagai alat tukar utang untuk menghindari inflasi. Sebagai contoh, jika seseorang membutuhkan 40 mayam emas, ia harus menyerahkan jaminan tanah sawah seluas satu naleh (kira-kira sepertiga hektare).
Dari sejumlah hasil kajian yang ada, setidaknya ada tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu:
1. Dominasi Pemanfaatan Tanah oleh Pemberi Utang
Temuan lapangan menunjukkan bahwa 77,8% informan menyatakan penerima gala (murtahin) memanfaatkan tanah sawah secara penuh. Artinya, selama utang emas belum dikembalikan, sawah tersebut dikelola oleh pemberi pinjaman, dan seluruh hasil panennya diambil oleh mereka tanpa memotong pokok utang.
Praktik ini telah menjadi semacam “bisnis” bagi pemilik modal di sejumlah wilayah tersebut. Mereka yang memiliki kelebihan emas cenderung hanya mau meminjamkan hartanya jika tanah jaminan tersebut bisa dikelola sepenuhnya. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik ini sangat berisiko jatuh pada riba, karena penerima gadai mengambil manfaat (hasil panen) atas utang yang diberikannya.
📚 Artikel Terkait
Hanya sebagian kecil kasus (8,3%) di mana penggadai tetap mengelola tanahnya namun membayar sewa kepada penerima gadai saat panen, atau sebaliknya (13,9%) penerima gala mengelola tanah namun membayar sewa kepada pemilik tanah. Model-model minoritas ini sebenarnya lebih mendekati prinsip keadilan, namun sayangnya bukan menjadi praktik mayoritas.
2. Ketiadaan Batas Waktu (Tempo)
Aspek kedua yang menonjol adalah ketidakpastian waktu. Sebanyak 83,3% informan menyatakan tidak ada penetapan batas waktu kapan utang harus dilunasi. Akad Gala Tanoh berlangsung terus-menerus sampai pihak penggadai mampu menebus kembali emasnya. Hal ini sering menyebabkan tanah tergadai selama puluhan tahun, bahkan bersifat turun-temurun. Situasi ini berpotensi merugikan pemilik tanah (rahin), karena akumulasi hasil panen yang diambil oleh pemberi utang selama bertahun-tahun bisa jadi jauh melebihi nilai utang emas yang dipinjam.
3. Fenomena Gala di Atas Gala
Kompleksitas bertambah dengan ditemukannya praktik “Gala di atas Gala” (8,3% kasus). Hal ini terjadi ketika penerima gala (pihak B) membutuhkan dana, sementara pemilik tanah asli (pihak A) belum mampu menebus utangnya. Pihak B kemudian menggadaikan kembali tanah tersebut kepada pihak ketiga (pihak C) tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik asli.
Secara hukum Islam dan etika sosial, ini adalah pelanggaran amanah. Barang jaminan seharusnya disimpan sebagai watsiqah (penguat kepercayaan), bukan dijadikan aset yang dipindahtangankan secara sepihak. Perselisihan sering muncul di kemudian hari akibat praktik ini, terutama jika pemilik asli ingin menebus tanahnya namun tanah tersebut sedang dikuasai oleh pihak ketiga.
Mengapa praktik yang tidak sesuai syariat ini masih langgeng di tengah masyarakat yang religius? Penelitian menemukan bahwa faktor “kebiasaan” dan “kebutuhan mendesak” menjadi pemicu utama. Masyarakat menganggap cara ini mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit dibandingkan berurusan dengan lembaga keuangan formal. Selain itu, ada unsur “keterpaksaan yang diikhlaskan”; pemilik tanah merasa tertolong saat butuh dana, sehingga merelakan tanahnya dikelola oleh pemberi utang.
Lalu dimana peran tokoh masyarakat? Sejumlah tokoh masyarakat seperti para teungku mengungkapkan bahwa sebenarnya mereka telah berupaya mensosialisasikan tata cara gadai yang benar melalui mimbar Jumat dan pengajian, tetapi mungkin belum cukup masif sehingga belum sepenuhnya dapat mengubah tradisi yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat.
Tantangan utamanya adalah pola pikir masyarakat yang memandang bahwa keuntungan hasil panen adalah hak wajar bagi pemberi pinjaman emas.
Khulasah
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Gala Tanoh di sejumlah wilayah di Aceh, secara umum masih belum selaras dengan prinsip Al-Rahnu dalam fiqh muamalah. Dominasi pemanfaatan tanah oleh penerima gadai secara penuh tanpa kompensasi pengurangan utang merupakan indikasi kuat terjadinya pengambilan manfaat atas utang (riba). Selain itu, ketiadaan batas waktu dan praktik menggadaikan ulang tanah orang lain menambah daftar ketidaksesuaian syariah.
Untuk meluruskan praktik ini, diperlukan pendekatan persuasif yang berkelanjutan.
Ulama dan cendekiawan ekonomi syariah perlu memberikan solusi konkret, bukan sekadar larangan. Misalnya, memperkenalkan akad Ijarah (sewa-menyewa) yang terpisah dari akad utang, atau sistem bagi hasil yang adil atas pengelolaan tanah gadai.
Disarankan agar masyarakat mulai membiasakan penetapan batas waktu pelunasan (jatuh tempo) untuk menghindari eksploitasi aset jangka panjang.
Dalam kasus kebutuhan mendesak di mana penerima gala perlu dana, harus ada izin eksplisit dari pemilik tanah sebelum menggadaikan ke pihak ketiga, atau mempertemukan langsung pemilik tanah dengan pemberi dana baru.
Kepada Pemerintah Aceh (Dinas Syariat Islam) dan lembaga keuangan syariah agar masing-masing dapat mengambil peran lebih aktif, misalnya dari sisi formalisasi regulasi, dan integrasi kearifan lokal dalam produk keuangan syariah.
Transformasi dari praktik adat menuju praktik yang syar’i membutuhkan kerjasama, waktu dan kesabaran. Namun, dengan potensi religiusitas masyarakat Aceh yang tinggi, perbaikan sistem Gala Tanoh menuju keadilan ekonomi bukanlah hal yang mustahil.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini