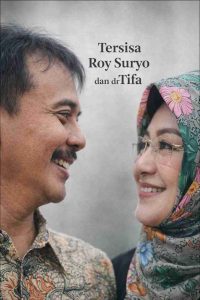Dengarkan Artikel
Oleh Fileski Walidha Tanjung
Saya lupa, hari ini ternyata 21 Februari. Hari yang sebetulnya paling kuhindari. Jika saja tanggal bisa ditawar, mungkin aku akan menegosiasikannya seperti orang menunda tagihan. Ulang tahun bagiku bukanlah perayaan, melainkan peringatan. Ia bukan kembang api, melainkan cermin. Dan cermin, seperti kata Socrates, “Hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dijalani.” Maka setiap 21 Februari, aku dipaksa bercermin.
Salah satu ucapan datang dari Ananda Sukarlan (komponis & pianis): “Selamat ulang tahun bro, semoga panjang umur dan semakin produktif berkarya.” Sebuah doa yang hangat, tetapi justru membuka ruang gelisah. Produktif untuk apa? Panjang umur untuk siapa? Dalam dunia yang semakin bising, produktivitas sering kali hanya berarti memperbanyak kebisingan.
Aku bertanya padanya, apa keresahanmu hari ini?
Ia menjawab dengan nada yang separuh lelah, separuh geram. Tentang sastrawan yang saling berkelahi, membuat kubu-kubu kecil, enggan saling mendengar ketika satu sama lain membaca puisi di panggung. Tentang kecenderungan membicarakan isu-isu besar seperti Palestina atau politik tanpa solusi, seolah retorika adalah tindakan. Tentang obsesi pada Nobel, padahal hadiah Lebaran saja tak didapat. Lalu tentang gagasan sinergi lintas disiplin—sastra dengan musik, sastra dengan seni rupa—namun dengan profesionalitas, bukan dengan penyair menyanyikan puisinya sendiri dengan suara fals, atau menciptakan lagu dari kecerdasan buatan yang dangkal.
Keresahan Ananda Sukarlan terasa seperti kritik terhadap zaman. Zaman di mana ekspresi kerap menggantikan kompetensi, dan sorotan panggung lebih penting daripada kualitas karya. Di titik ini aku teringat peringatan Alasdair MacIntyre bahwa krisis moral modern lahir ketika praktik kehilangan tradisinya, ketika keahlian tidak lagi berakar pada disiplin, melainkan pada citra. Tanpa disiplin, seni menjadi sekadar performa diri.
Fenomena pembuatan lagu melalui AI menjadi simbol paling terang dari krisis ini. Seseorang mengetikkan prompt, menunggu satu menit, lalu merasa telah mencipta. Ada kepuasan instan, ada sensasi menjadi “kreator”, padahal proses panjang yang membentuk kepekaan musikal—latihan, kegagalan, pendalaman teori, dialog dengan tradisi—tidak pernah dijalani. Martin Heidegger pernah mengingatkan, “Teknologi bukanlah sekadar alat; ia adalah cara kita memandang dunia.” Ketika teknologi memampatkan proses menjadi instan, kita pun mulai memandang kreativitas sebagai sesuatu yang bisa diproduksi tanpa askese.
Ananda melontarkan kalimat yang provokatif: “Karena kita merasa bodoh, kita ciptakan kepintaran yang palsu.” Dalam nadanya ada ironi sekaligus ketakutan. Kita cukup pintar untuk menciptakan kecerdasan buatan, tetapi cukup bodoh untuk bergantung padanya tanpa kritik. Di sini aku teringat peringatan C.S. Lewis bahwa manusia modern berisiko menjadi “manusia tanpa nurani”—cerdas secara teknis, tetapi miskin kedalaman moral dan imajinatif. Kita bisa membuat mesin yang menulis puisi, tetapi apakah kita masih mampu merasakan puisi?
Apa yang dibanggakan dari lagu yang dibuat dalam semenit? Ketika aku menghadiri konser seorang musisi, ada kebanggaan yang lahir bukan hanya dari nada, tetapi dari cerita di baliknya. Aku tahu ia berlatih bertahun-tahun. Aku tahu ada sejarah kegagalan, ada peluh, ada disiplin. Di balik karya ada proses; di balik proses ada karakter. Aristoteles menyebut keutamaan sebagai hasil pembiasaan—kita menjadi apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Jika kreativitas dipadatkan menjadi satu klik, kebiasaan apa yang sedang kita bangun? Keutamaan apa yang sedang kita latih?
Zaman ini tampaknya terobsesi pada hasil, bukan pada proses. Padahal nilai sebuah karya seringkali justru terletak pada narasi yang melahirkannya. Søren Kierkegaard pernah berkata, “Hidup hanya dapat dipahami dengan melihat ke belakang, tetapi harus dijalani dengan melihat ke depan.” Tanpa proses, kita kehilangan masa lalu untuk dipahami. Tanpa sejarah penciptaan, karya menjadi yatim.
Keresahan Ananda tentang sastrawan yang saling bertengkar pun sebenarnya berakar pada hal yang sama: hilangnya kesadaran akan tradisi dan tujuan bersama. Jika sastra dipandang sebagai panggung ego, maka yang lahir adalah kubu. Tetapi jika ia dipandang sebagai medan pengabdian pada bahasa dan kemanusiaan, maka yang lahir adalah dialog. Paulo Freire mengingatkan, “Dialog adalah pertemuan antara manusia untuk menamai dunia.” Tanpa dialog, kita hanya saling meneriakkan nama kita sendiri.
Kritik terhadap AI bukanlah penolakan terhadap teknologi. Ia adalah penolakan terhadap kemalasan eksistensial. Teknologi bisa menjadi alat sinergi lintas disiplin—mendekatkan sastra dengan musik, mempertemukan puisi dengan seni rupa—asal ia tidak menggantikan kedalaman dengan kemudahan. Sinergi yang dibayangkan Ananda bukanlah pencampuran asal-asalan, melainkan perjumpaan dua disiplin yang masing-masing matang. Yang bisa menulis, menulis dengan baik. Yang bisa menyanyi, menyanyi dengan baik. Bukan semuanya menjadi serba-bisa yang dangkal.
Dalam konteks isu kontemporer, mungkin yang kita alami bukan sekadar krisis sastra atau musik, melainkan krisis makna. Kita hidup dalam era di mana kecepatan dianggap keunggulan, padahal kecepatan seringkali mengorbankan perenungan. Kita merayakan kecerdasan buatan, tetapi jarang merawat kecerdasan alami—kemampuan untuk sabar, untuk tekun, untuk gagal dengan elegan. Apakah kita benar-benar ingin menjadi generasi yang lebih cepat tetapi lebih dangkal?
Pada 21 Februari ini, ulang tahunku terasa seperti pengadilan kecil atas diriku sendiri. Apakah aku menulis untuk memperbanyak konten, atau untuk memperdalam makna? Apakah aku mengkritik zaman hanya sebagai gaya, atau sebagai tanggung jawab? Apakah aku sedang membangun tradisi, atau sekadar membangun citra?
Mungkin pertanyaan paling jujur bukanlah bagaimana membuat karya yang hebat, melainkan bagaimana menjadi manusia yang layak melahirkan karya. Jika kecerdasan buatan terus berkembang, apakah kita juga akan mengembangkan kebijaksanaan alami? Jika teknologi mampu membuat kita tampak pintar, apakah kita masih peduli untuk benar-benar menjadi bijak?
Ulang tahun, akhirnya, bukan tentang bertambahnya usia, melainkan tentang bertambahnya kesadaran. Di tengah dunia yang memuja yang instan, beranikah kita memilih yang mendalam? Di tengah tepuk tangan untuk hasil cepat, beranikah kita setia pada proses yang sunyi? Dan ketika suatu hari kita berdiri di hadapan karya kita sendiri, dapatkah kita berkata dengan jujur bahwa dibaliknya ada cerita perjuangan, bukan sekadar prompt satu menit?
Mungkin hanya dengan pertanyaan-pertanyaan itulah 21 Februari layak dirayakan—bukan sebagai pesta, melainkan sebagai keberanian untuk tetap menjadi manusia di tengah godaan menjadi artifisial. (*)
Fileski Walidha Tanjung adalah penulis dan penyair kelahiran Madiun 1988. Aktif menulis puisi, esai, dan cerpen di berbagai media nasional. Profil Undagi Balai Bahasa Jawa Timur 2026.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini