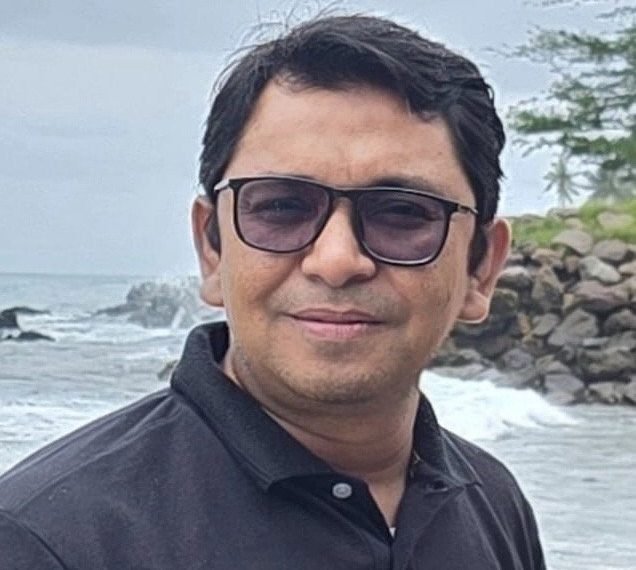Dengarkan Artikel
Oleh: Azharsyah Ibrahim*
Dalam terminologi universal, sehelai kain putih yang diacungkan di medan tempur lazim diartikan sebagai simbol kapitulasi, sebuah isyarat menyerah kalah dan menanggalkan senjata. Namun, bagi masyarakat Aceh, kawasan yang sejarahnya terukir dengan tinta perlawanan abadi, semantik “bendera putih” memiliki resonansi yang jauh melampaui definisi konvensional tersebut.
Putih, di Serambi Mekkah, bukanlah representasi kekalahan, melainkan sebuah pernyataan kultural, historis, dan teologis yang mendalam tentang martabat, kedaulatan moral, dan, pada puncaknya, penyerahan diri total kepada Sang Pencipta.
Fenomena berkibarnya bendera putih di sejumlah lokasi di Aceh belakangan ini, yang dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap respons negara, khususnya dalam penanganan bencana, tidak boleh dibaca hanya sebagai ekspresi keputusasaan biasa.
Pemerintah wajib mendekati gejala sosial ini dengan kacamata historis dan psikologis yang jernih, bukan sekadar respons administratif atau retorika defensif. Tanpa pemahaman komprehensif mengenai akar identitas Aceh yang khas—yang ditempa oleh perang panjang dan nilai-nilai keislaman yang mengakar—negara hanya akan terjebak pada solusi permukaan, gagal menyentuh substansi luka dan ketidakpercayaan yang sedang menganga di tengah publik.
Perlawanan Abadi dan Memori Kolektif
Sejarah mencatat, Aceh sebagai wilayah yang memiliki otonomi moral dan militer yang unik. Wilayah ini tidak pernah benar-benar dapat ditundukkan secara penuh oleh kolonialisme. Atjeh Oorlog (Perang Aceh) yang pecah sejak 1873 bukan hanya menjadi konflik terlama yang dihadapi kolonial Belanda di Nusantara, tetapi juga menjadi perang atrisi yang menguras habis kas dan mentalitas serdadu mereka. Bahkan, sejumlah sejarawan menyebutnya sebagai kuburan bagi ambisi kolonial Belanda.
Ketika para sultan dan panglima besar seperti Teuku Umar telah gugur atau ditangkap, api perlawanan rakyat tidak pernah padam, melainkan bertransformasi menjadi serangan sporadis yang bersifat personal dan sangat ideologis. Fenomena ini diabadikan oleh orientalis Christiaan Snouck Hurgronje—penasihat Belanda untuk urusan pribumi—dalam karyanya De Atjehers (Orang Aceh), yang kemudian memunculkan istilah Aceh Pungo (Aceh Gila) atau Atjeh-moord.
Istilah ini merujuk pada kegilaan perlawanan yang membuat setiap individu rakyat Aceh berpotensi menjadi ancaman mematikan bagi serdadu kolonial.
Perlawanan ini tidak lagi didominasi oleh strategi militer, melainkan oleh keyakinan teologis-ideologis untuk mencapai martabat syahid.
Paul van’t Veer dalam bukunya De Atjeh-oorlog (Perang Aceh) menegaskan bahwa konflik di Aceh merupakan beban finansial dan psikologis terbesar sepanjang sejarah Kerajaan Belanda di Hindia Timur. Trauma kolektif inilah yang menjadi penentu sikap Belanda pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Hal ini terkonfirmasi ketika saya berkunjung ke Perpustakaan Universitas Leiden beberapa tahun lalu, seorang kurator menjelaskan bahwa biaya dan korban jiwa Perang Aceh jauh melampaui konflik kolonial lain dan meninggalkan trauma psikologis bagi Kerajaan Belanda.
Dampak trauma sejarah ini sangat signifikan, ketika NICA (Belanda) kembali ke Indonesia pada tahun 1945, mereka sama sekali tidak berkeinginan kembali ke wilayah Aceh. Secara de facto dan de jure, Aceh saat itu bisa dikatakan sebagai wilayah yang telah berdiri sendiri dan aman dari jangkauan Belanda.
Ironi historisnya, di tengah kondisi seperti itu, para pemimpin dan rakyat Aceh saat itu justru menunjukkan semangat kebersamaan dan keislaman yang tulus terhadap perjuangan Republik Indonesia yang baru seumur jagung. Mereka tidak memilih untuk eksklusif, melainkan menjadi “Daerah Modal” bagi eksistensi negara baru tersebut.
Rakyat Aceh secara tulus meripee (bersama-sama mengumpulkan donasi) dari seluruh lapisan masyarakat untuk membeli pesawat pertama RI, yakni pesawat Dakota RI-001 “Seulawah”, yang menjadi tulang punggung diplomasi dan perjuangan udara Indonesia.
Tidak hanya itu, Aceh juga mengirimkan sejumlah laskar dan pasukan ke Front Medan Area untuk membantu melawan tentara Belanda. Kontribusi krusial ini menjadikan narasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran sentral Aceh.
Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tanpa keikhlasan Aceh sebagai “Daerah Modal,” sejarah awal Republik mungkin akan sangat berbeda dan berakhir lebih dini.
📚 Artikel Terkait
Bendera Putih dalam Narasi Teologi
Berdasarkan latar belakang sejarah yang heroik dan penuh pengorbanan tersebut, sangat tidak logis, jika kini masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih hanya sebagai tanda “menyerah” pada kesulitan hidup.
Bendera putih yang muncul di tengah krisis bencana adalah simbol yang jauh lebih politis dan teologis, yaitu mosi tidak percaya yang paling diam dan paling kuat terhadap efektivitas pemerintahan.
Kekecewaan ini dipicu oleh kelambanan dan arogansi struktural negara dalam merespons penderitaan rakyat.Ketika jalur transportasi vital di pegunungan tertutup longsor dan lumpur, memaksa warga berjalan kaki berkilo-kilometer demi mendapatkan bahan makanan pokok, sementara para pejabat tetap nyaman dengan retorika di ruang ber-AC, di situlah nurani publik terkoyak.
Kemarahan publik mencapai puncaknya ketika hambatan birokrasi, atau bahkan larangan, diberlakukan terhadap pihak asing dan relawan dalam negeri yang berniat memberikan bantuan.
Masyarakat merasakan dibiarkan dalam keterisolasian, dalam proses “mati pelan-pelan.” Dalam konteks ini, bendera putih adalah alarm bahaya. Ia adalah sinyal bahwa rakyat telah mencapai titik nadir dalam mengharapkan aksi konkret dari pemerintah.
Ketika struktur formal negara dianggap gagal total dalam menjalankan fungsi fundamentalnya, yaitu melindungi segenap bangsa, masyarakat Aceh kembali ke akar fundamentalnya, bertawakkal kepada Allah.
Filosofi ini menjelaskan mengapa ketika tangan-tangan kekuasaan dianggap tidak lagi mampu merengkuh kesulitan rakyat, maka rakyat memilih untuk “melambaikan tangan” kepada langit. Kain putih dikibarkan sebagai tanda pengakuan spiritual: Lā hawla wa lā quwwata illā billāh—tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah semata.
Dimensi spiritual inilah yang menjadi kunci ketangguhan mental kolektif Aceh. Pasca-tragedi Tsunami 2004 yang meluluhlantakkan Aceh dan merenggut ratusan ribu jiwa, kita tidak pernah mendengar kasus bunuh diri massal akibat depresi kehilangan harta dan keluarga.
Dalam logika materialisme, kehilangan segalanya dalam sekejap adalah alasan yang kuat untuk mengakhiri hidup. Namun, bagi masyarakat Aceh, “putih” adalah warna kain kafan sekaligus warna kesucian niat. Penderitaan di dunia hanyalah ujian sementara yang harus dihadapi dengan kesabaran.
Bendera putih, dalam konteks ini adalah manifestasi dari kepasrahan total, ketika harapan kepada manusia telah pupus, maka hubungan vertikal langsung kepada Sang Pencipta menjadi satu-satunya sandaran.
Panggilan untuk Kembali ke Khittah Keadilan
Pemerintah seharusnya merasa malu, bukan malah merasa terancam atau bersikap defensif dengan kibaran bendera putih tersebut. Setiap helai kain putih yang berkibar di pelosok Aceh adalah tamparan keras bagi efektivitas dan empati pelayanan publik.
Jangan sampai narasi historis “Daerah Modal” yang dulu disumbangkan Aceh dengan penuh keikhlasan, kini berbalas dengan pengabaian yang sistematis dan terstruktur di masa sulit.
Negara harus hadir melampaui sebatas retorika dan janji-janji politik. Solusi yang mendesak adalah aksi nyata seperti perbaikan akses transportasi di daerah bencana, percepatan distribusi logistik, dan penghapusan segala hambatan birokrasi bagi relawan kemanusiaan, baik lokal maupun internasional.
Jangan biarkan rakyat Aceh merasa terasing dan ditinggalkan di tanah yang mereka perjuangkan dengan darah, air mata, dan pengorbanan historis.
Melihat bendera putih di Aceh dengan kacamata sempit “menyerah” adalah sebuah kegagalan literasi sejarah dan budaya. Pemerintah dan pemangku kebijakan harus mampu membaca bahwa bendera putih adalah pesan berlapis yang sangat kuat, diantaranya:
Pertama, ia adalah pengingat akan loyalitas historis Aceh yang tidak perlu diragukan, yang harusnya dibalas dengan keadilan.
Kedua, ia adalah kritik pedas terhadap ketimpangan sosial dan kegagalan birokrasi dalam merespons krisis kemanusiaan. Ketiga, dan yang paling krusial, ia adalah pengingat bahwa rakyat memiliki batas kesabaran. Ketika batas itu terlampaui, mereka akan kembali ke titik nol, yaitu hanya bersandar pada Tuhan, bukan pada janji-janji kekuasaan.
Sudah saatnya retorika diubah menjadi aksi nyata dan empati struktural. Jangan biarkan rakyat yang dulu menjadi donatur kemerdekaan bangsa ini, kini harus mengibarkan bendera putih karena merasa asing dan terlupakan di tanahnya sendiri.
Bendera putih di Aceh adalah panggilan darurat untuk kembali ke khittah keadilan. Sebab, di balik kain putih yang berkibar itu, tersimpan martabat bangsa yang tak boleh dibiarkan layu oleh pengabaian.
—
*Penulis adalah Guru Besar UIN Ar-Raniry dan pengamat sosial kemasyarakatan.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini