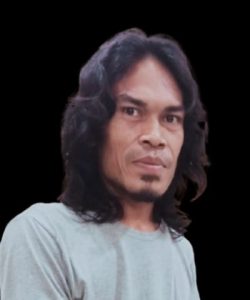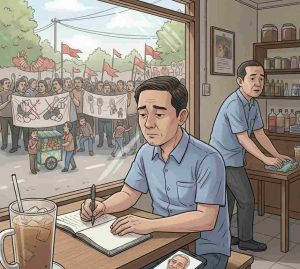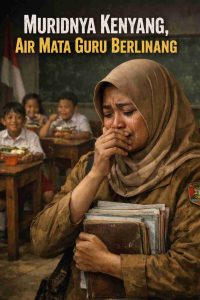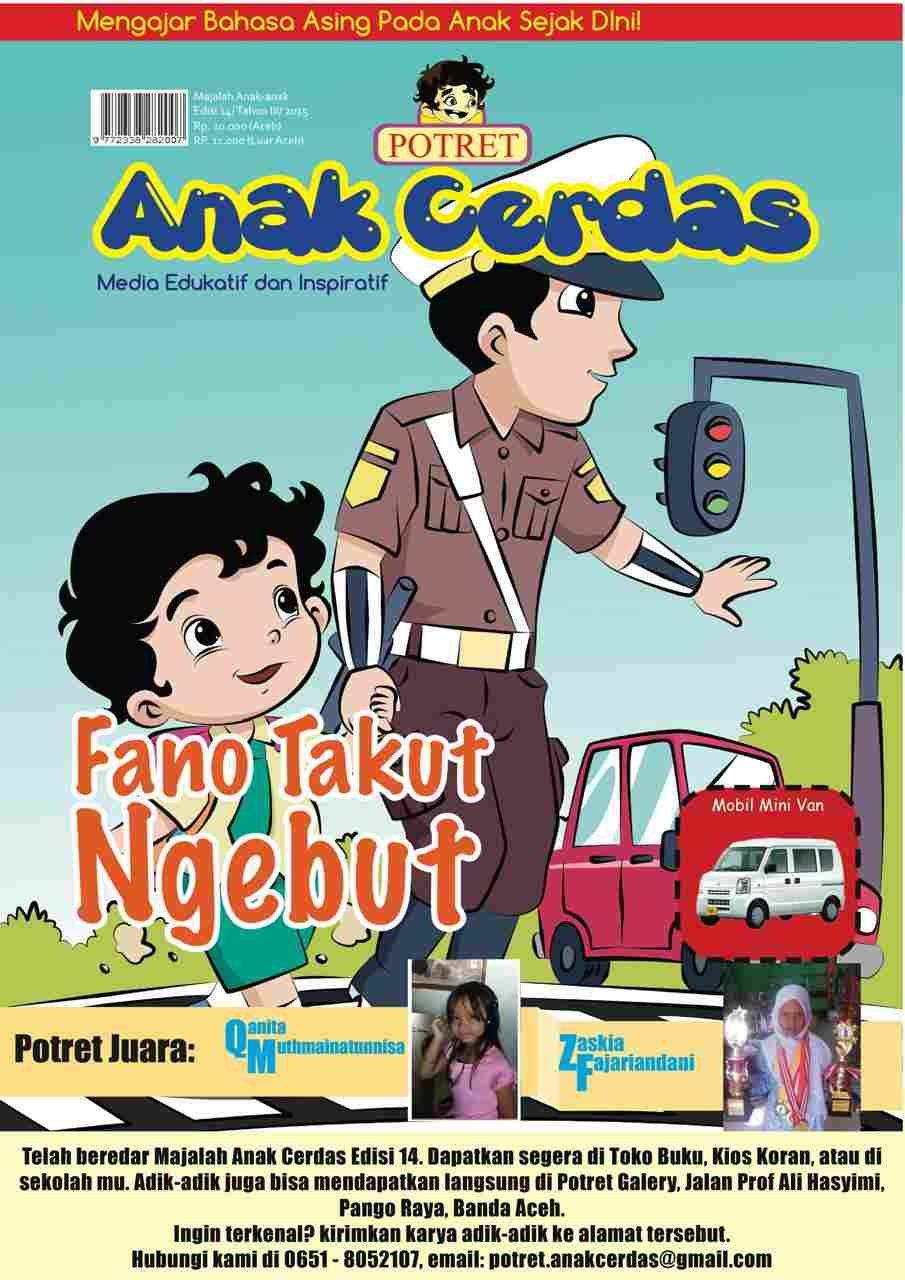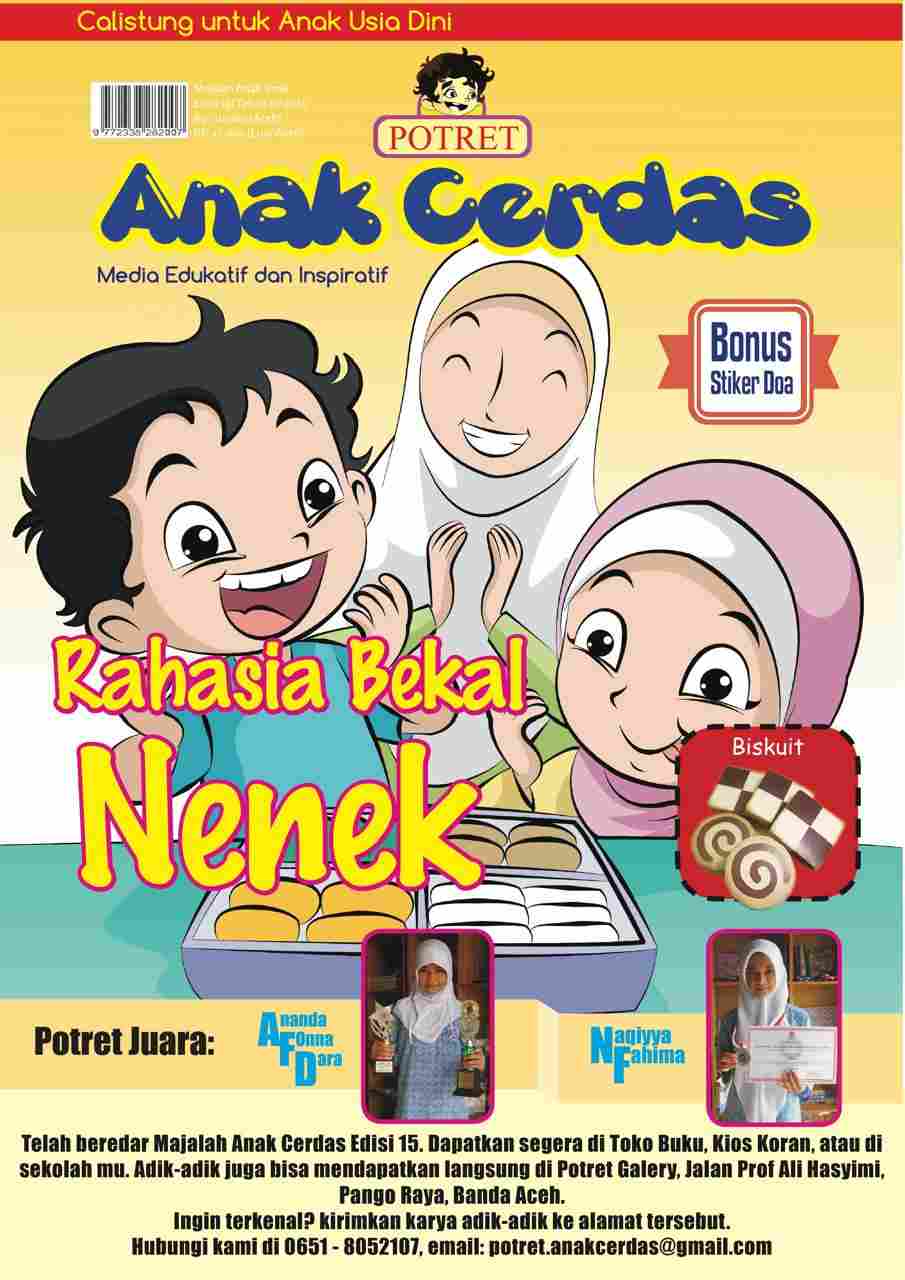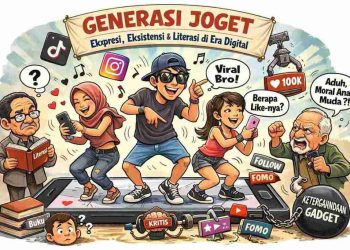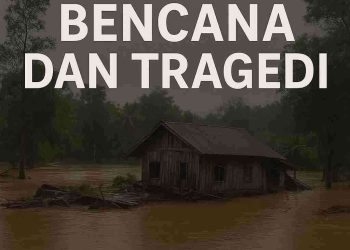Dengarkan Artikel
Penyerahan Kekuasaan yang Menyakitkan di Kutaradja
Oleh: Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh, M.Si.
Dosen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh
Pada tanggal 10 Januari 1903, sebuah babak kelam dalam sejarah Aceh ditorehkan. Di Kutaradja (sekarang Banda Aceh), Sultan Alauddin Muhammad Daudsyah II, Sultan terakhir Kesultanan Aceh Darussalam, mengakhiri perlawanan panjangnya dengan menyerahkan diri kepada Pemerintah Kolonial Hindia Belanda (Juliana, 2021: 1). Momen ini, yang sering kali disalahpahami sebagai penyerahan mutlak kekuasaan Kesultanan kepada Belanda, adalah sebuah puncak dari perjuangan heroik yang diwarnai keputusasaan dan tekanan psikologis mendalam. Lebih dari sekadar seremoni formal, penyerahan ini adalah cerminan dari tragedi pribadi Sultan dan dampak brutal dari perang yang berkepanjangan.
Selama ini, narasi populer seringkali mengabaikan fakta penyerahan ini, atau jika diakui, menafsirkannya sebagai tindakan pribadi Sultan yang terpisah dari kedaulatan Kesultanan. Namun, foto-foto sejarah yang menunjukkan Sultan Muhammad Daudsyah berdiri di hadapan para petinggi Belanda adalah bukti tak terbantahkan dari momen tersebut (Sudirman, 2016). Perdebatan muncul, apakah ini adalah penyerahan kekuasaan negara atau sekadar penyerahan diri seorang individu yang putus asa? Bagi banyak pihak, ini adalah yang kedua. Sultan, seorang ayah dan suami, dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa istri dan anak-anaknya telah ditangkap oleh Marsose kolonial yang kejam (Fachry Ali, 1994: 153). Dalam kondisi tertekan ini, penyerahan diri menjadi pilihan yang mungkin terlihat paling manusiawi untuk menyelamatkan keluarganya dari penderitaan lebih lanjut. Ini adalah sebuah pilihan yang menggema dengan tragis, bukan sebagai kekalahan militer murni, tetapi sebagai penyerahan moral yang dipaksakan.
Sebelum penyerahan ini, Aceh telah lama menjadi duri dalam daging bagi ambisi kolonial Belanda. Selama puluhan tahun, Kesultanan Aceh Darussalam, yang dikenal sebagai kekuatan maritim dan pusat Islam yang berpengaruh di Nusantara (Hadi, 2003: 48), telah dengan gagah berani melawan invasi Belanda. Perlawanan ini diperkuat oleh semangat jihad yang membara dalam diri rakyat Aceh, sebuah konsep yang dipahami secara mendalam dan diabadikan dalam berbagai karya sastra seperti Hikayat Prang Sabi (Hadi, 2011: 183). Namun, kekuatan militer kolonial yang lebih unggul, taktik bumi hangus, dan strategi licik Belanda, termasuk penggunaan pasukan Marsose yang brutal, secara perlahan mengikis kekuatan Aceh.
Aceh Pungoe
Puncak dari kondisi psikologis yang hancur pasca-penyerahan Kesultanan adalah munculnya fenomena “Aceh Pungoe” atau “Aceh Moorden“. Ini adalah kondisi di mana individu-individu Aceh, yang tertekan oleh kekalahan, kehancuran sosial, dan hilangnya kedaulatan, melakukan tindakan-tindakan bunuh diri atau serangan tunggal terhadap Belanda. Fenomena ini bukan sekadar tindakan kriminal, melainkan manifestasi ekstrem dari trauma kolektif, rasa malu, dan keputusasaan yang mendalam akibat penaklukan brutal. Aceh Pungoe adalah jeritan jiwa yang terbungkam, sebuah bukti nyata bahwa meskipun secara formal kekuasaan telah berpindah tangan, semangat perlawanan dan rasa sakit tidak pernah mati.
Penyerahan Sultan Muhammad Daudsyah II pada 10 Januari 1903 adalah sebuah titik balik yang mengubah lanskap Aceh selamanya. Ini adalah akhir dari sebuah era Kesultanan yang telah berdiri selama berabad-abad, menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kekuatan dunia, termasuk Kesultanan Ottoman (Göksoy, 2011: 65). Namun, ini juga adalah awal dari babak baru perlawanan, yang meskipun tidak lagi berbentuk kerajaan, terus membara dalam hati rakyat Aceh, melahirkan pemberontakan-pemberontakan selanjutnya sebagai bentuk penolakan terhadap penjajahan (Compton, 2021: 134). Penyerahan ini, yang sarat dengan drama dan tragedi, adalah pengingat pahit akan harga yang harus dibayar oleh sebuah bangsa ketika kedaulatan dirampas.
Setelah penyerahan diri pada 10 Januari 1903, kondisi Sultan Alauddin Muhammad Daudsyah II sangat berubah. Ia tidak lagi memimpin Kesultanan Aceh, melainkan menjadi tawanan Belanda dan diasingkan.
Setelah menyerah, Sultan Daud Syah awalnya ditahan di Kampung Keudah, Aceh. Meskipun dalam tahanan, ia masih memiliki pengaruh dan sempat mendukung para pejuang Aceh untuk melanjutkan perlawanan terhadap Belanda.
Karena pengaruhnya yang masih kuat dan kekhawatiran Belanda akan terus berlanjutnya perlawanan, pada 24 Desember 1907, Belanda membuang Sultan Daud Syah beserta keluarganya ke Ambon. Kemudian, pada tahun 1918, ia dipindahkan lagi ke Batavia (sekarang Jakarta).Sultan Muhammad Daudsyah menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan di Batavia. Ia meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1939 di Meester Cornelis, Batavia (sekarang Jatinegara, Jakarta).
Jenazah Sultan Muhammad Daudsyah dimakamkan di Pekuburan Umum Kemiri, Rawamangun, Jakarta Timur. Seluruh kekayaan Sultan dirampas dan dijadikan milik kolonial Belanda sesuai dengan asas hukum perang Reght van Over Winning.Setelah penyerahan Sultan Muhammad Daudsyah II dan berakhirnya Perang Aceh, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menerapkan asas hukum perang yang mereka sebut “Recht van Overwinning” atau Hak Kemenangan. Berdasarkan asas ini, Belanda mengklaim bahwa seluruh kekayaan Kesultanan Aceh, termasuk harta pribadi Sultan, dianggap sebagai rampasan perang dan secara sah menjadi milik pemerintah kolonial.
Ini adalah praktik umum dalam hukum perang pada masa itu, di mana pihak yang menang berhak atas properti dan wilayah pihak yang kalah. Bagi Belanda, penyerahan Sultan menandai kemenangan mutlak mereka di Aceh, sehingga mereka merasa berhak untuk menyita dan menguasai semua aset yang terkait dengan Kesultanan. Penyitaan ini tidak hanya mencakup harta benda bergerak, tetapi juga kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan.
Tindakan perampasan ini adalah salah satu konsekuensi pahit dari kekalahan dan penaklukan. Bagi rakyat Aceh, ini adalah kerugian besar yang menambah penderitaan setelah puluhan tahun berperang dan kehilangan kedaulatan. Meskipun Sultan telah menyerah dan diasingkan, perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda terus berlanjut di bawah pimpinan ulama dan pejuang lainnya hingga Aceh akhirnya bergabung dengan Republik Indonesia.
Setelah penyerahan Sultan Alauddin Muhammad Daudsyah II pada tahun 1903, tidak ada suksesi kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam secara formal. Kesultanan secara de facto dianggap dihapuskan oleh Belanda setelah penyerahan Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah II. Meskipun demikian, terdapat beberapa interpretasi dan kenyataan di lapangan mengenai kelanjutan perlawanan dan pusat-pusat pengaruh di Tiro (ulama) dan Keumangan (uleebalang).
Perlawanan dilanjutkan oleh Para Ulama
📚 Artikel Terkait
Setelah penyerahan Sultan, perlawanan terhadap Belanda tidak serta merta berhenti. Para ulama, terutama dari daerah seperti Tiro di Pidie, memainkan peran yang sangat penting dalam melanjutkan perjuangan bersenjata. Mereka menjadi simbol perlawanan dan memimpin gerakan gerilya yang didasarkan pada semangat jihad (Hadi, 2011: 183). Ini bukan kelanjutan kekuasaan dalam arti monarki, melainkan kelanjutan kepemimpinan spiritual dan perlawanan rakyat yang terorganisir di bawah panji-panji agama. Ulama menjadi pusat kekuatan moral dan perlawanan di tengah kekosongan kekuasaan formal Kesultanan.
Interpretasi bahwa kekuasaan dilimpahkan kepada lingkaran uleebalang di Keumangan merujuk pada upaya Belanda untuk bekerja sama dengan sebagian uleebalang demi menstabilkan wilayah dan mengakhiri perlawanan. Belanda memang menerapkan strategi “politik kolaborasi” dengan penguasa lokal di berbagai wilayah untuk memperkuat kendali mereka (The Aceh War – Research Explorer – Universiteit van Amsterdam). Namun, ini tidak berarti Sultan secara sukarela melimpahkan kekuasaan kepada mereka. Justru, Sultan Muhammad Daudsyah II dikenal sangat sakit hati dan kecewa dengan beberapa uleebalang yang dianggap telah mengkhianati perjuangan Aceh selama Perang Aceh yang panjang (1873-1903). Pengkhianatan ini seringkali berbentuk kerja sama dengan Belanda, baik karena tekanan, iming-iming jabatan, atau perbedaan pandangan strategis. Sultan sendiri terpaksa menyerah karena keluarganya ditawan, bukan karena ia percaya pada uleebalang kolaborator.
James Siegel dalam bukunya The Rope of God (2000) menganalisis secara mendalam bagaimana penaklukan Belanda dan berakhirnya Kesultanan Aceh mengubah tatanan sosiologis, budaya, dan spiritual masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari. Siegel melihat perubahan ini bukan hanya sebagai kehancuran, tetapi juga sebagai proses adaptasi dan redefinisi identitas.
Siegel berpendapat bahwa sebelum penaklukan Belanda, masyarakat Aceh, meskipun memiliki berbagai kelompok sosial, tidak diatur dalam hierarki yang kaku. Namun, setelah perang dan hilangnya Sultan sebagai pusat kekuasaan, masyarakat menjadi lebih “teratomisasi” atau terpecah-pecah. Kekuatan tradisional para uleebalang (kepala daerah) yang sebelumnya memiliki peran penting, mulai memudar atau beralih fungsi di bawah administrasi kolonial. Hal ini menciptakan kekosongan dalam struktur sosial yang sebelumnya terintegrasi secara vertikal.
Penaklukan Belanda juga membawa perubahan signifikan dalam pola ekonomi. Siegel mencatat bahwa meskipun petani tetap dekat dengan tanah mereka, banyak laki-laki harus mencari penghasilan tambahan di luar desa mereka. Ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi baru dan perubahan dalam cara masyarakat mencari nafkah, yang mungkin disebabkan oleh kontrol kolonial atas sumber daya dan perdagangan.
Salah satu dampak paling krusial yang diuraikan Siegel adalah bagaimana Islam menjadi “tali Tuhan” (The Rope of God) yang menyatukan kembali masyarakat Aceh di tengah kekacauan dan perubahan. Dengan hilangnya Sultan sebagai pemimpin politik dan spiritual, para ulama (cendekiawan agama) mengambil peran yang lebih sentral. Mereka berusaha mengarahkan masyarakat Aceh menjauh dari praktik adat (adat) lokal yang dianggap kurang ortodoks menuju kehidupan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam.
Siegel menyoroti pentingnya konsep akal (rasionalitas) dalam budaya Aceh, terutama dalam konteks penderitaan dan kehilangan. Ia berpendapat bahwa kemampuan untuk mengendalikan kesedihan dan nafsu melalui akal adalah bagian esensial dari menjadi manusia yang utuh menurut pandangan Aceh. Para ulama mengajarkan penolakan diri dan rasionalitas di atas ikatan sosial atau pemuasan keinginan. Ini menjadi mekanisme budaya dan spiritual bagi masyarakat untuk menghadapi trauma dan kehancuran akibat perang dan penaklukan.
Jihad sebagai Narasi Perlawanan dan Makna
Meskipun tidak secara langsung membahas “Recht van Overwinning,” Siegel menganalisis bagaimana narasi jihad, seperti yang terungkap dalam Hikayat Prang Sabi (Kisah Perang Suci), memberikan makna dan tujuan bagi perlawanan Aceh terhadap Belanda. Ini adalah dimensi spiritual yang kuat, di mana perjuangan melawan penjajah dipandang sebagai kewajiban agama. Meskipun Kesultanan runtuh, semangat perlawanan yang dijiwai oleh Islam tetap hidup.
Secara keseluruhan, Siegel menggambarkan bahwa penaklukan Belanda tidak hanya menghancurkan struktur politik lama, tetapi juga memaksa masyarakat Aceh untuk mencari cara-cara baru dalam memahami diri mereka dan dunia di sekitar mereka. Dalam proses ini, Islam dan kepemimpinan ulama menjadi jangkar yang kuat, membantu masyarakat Aceh untuk mempertahankan identitas dan kohesi sosial mereka di tengah tekanan kolonial yang masif.
Setelah penyerahan Sultan, kekuasaan Kesultanan Aceh secara resmi berakhir. Namun, perlawanan rakyat terus berlanjut, dengan ulama menjadi motor penggerak utama perjuangan, sementara beberapa uleebalang justru berpihak pada Belanda, yang menimbulkan kekecewaan mendalam bagi Sultan dan pejuang lainnya.[]
Bibliografi
Ali, Fachry. 1994. The revolts of the nation-state builders: a comparative study of the Acehnese Darul Islam and the west Sumatran PRRI rebellions (1953-1962). Diss. Monash University.
Compton, Boyd R. 2021. Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-Surat Rahasia Boyd R. Compton. LP3ES.
Göksoy, İsmail Hakkı. 2011. “Ottoman-Aceh relations as documented in Turkish sources.” Dalam Mapping the Acehnese Past, 65-96.
Hadi, Amirul. 2003. Islam and state in Sumatra: A study of seventeenth-century Aceh. Vol. 48. Brill.
Hadi, Amirul. 2011. “CHAPTER IX: Exploring Acehnese understandings of jihad: A study of the Hikayat prang sabi.” Dalam Mapping the Acehnese Past, 183-197. Brill.
Juliana, Nita. 2021. Eksistensi Kerajaaan Aceh Darussalam Pasca Pengasingan Sultan Muhammad Daud Syah (1906-1942). Diss. UPT. Perpustakaan.
Ozay, Mehmet. 2011. “The sultanate of Aceh Darussalam as a constructive power.” International Journal of Humanities and Social Science 1(11): 274-284.
Sudirman, Sudirman. 2016. Kronologis para Sultan Aceh. No. 54. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Siegel, James T. The rope of God. University of Michigan Press, 2000.
Takeshi, Ito. 1984. The world of the adat Aceh: A historical study of the sultanate of Aceh. The Australian National University (Australia).
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini