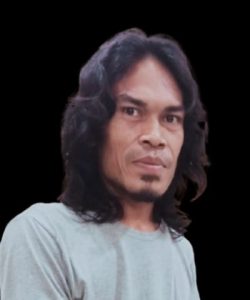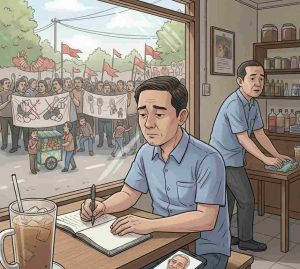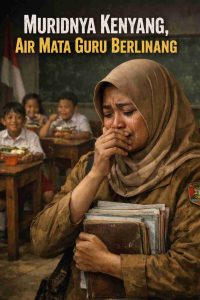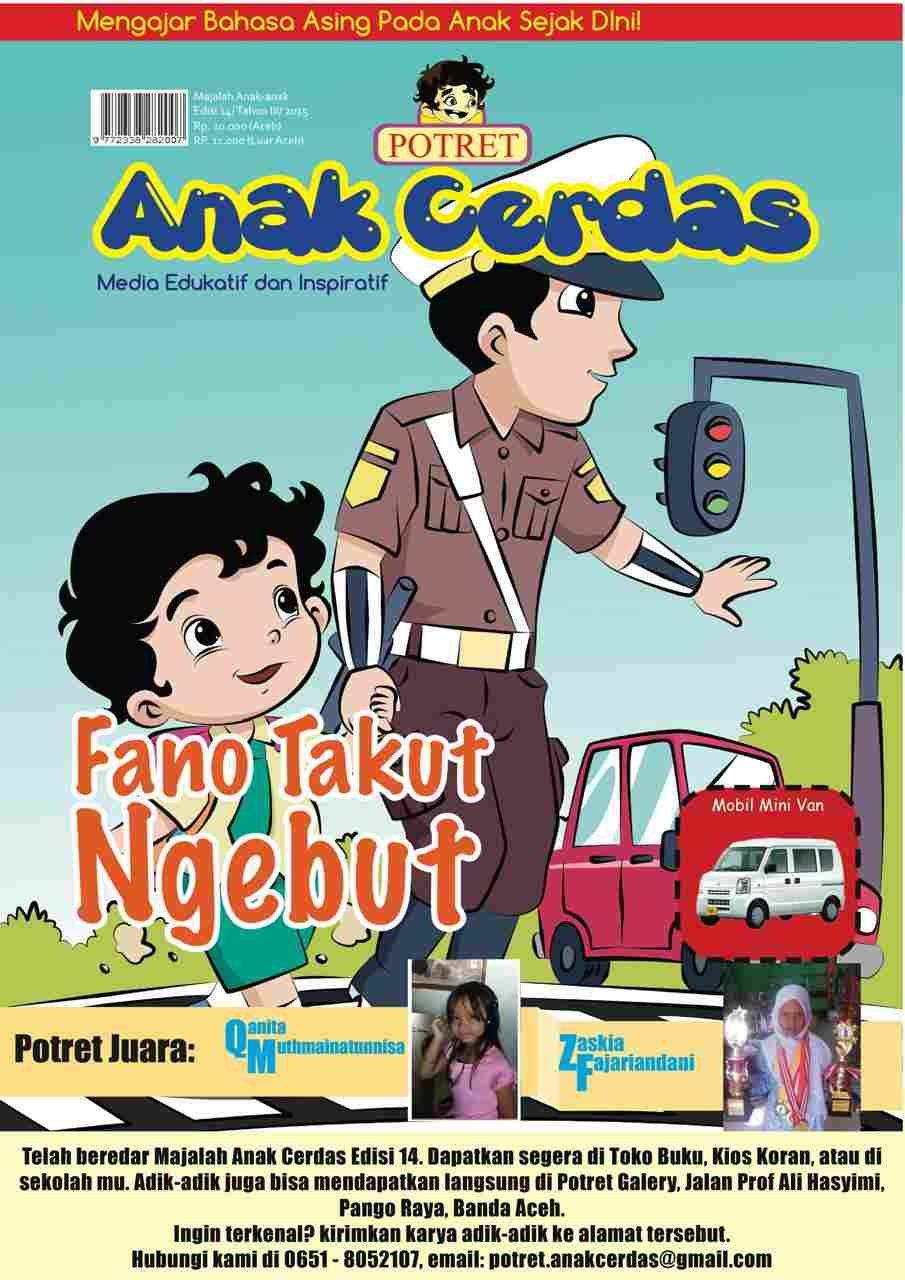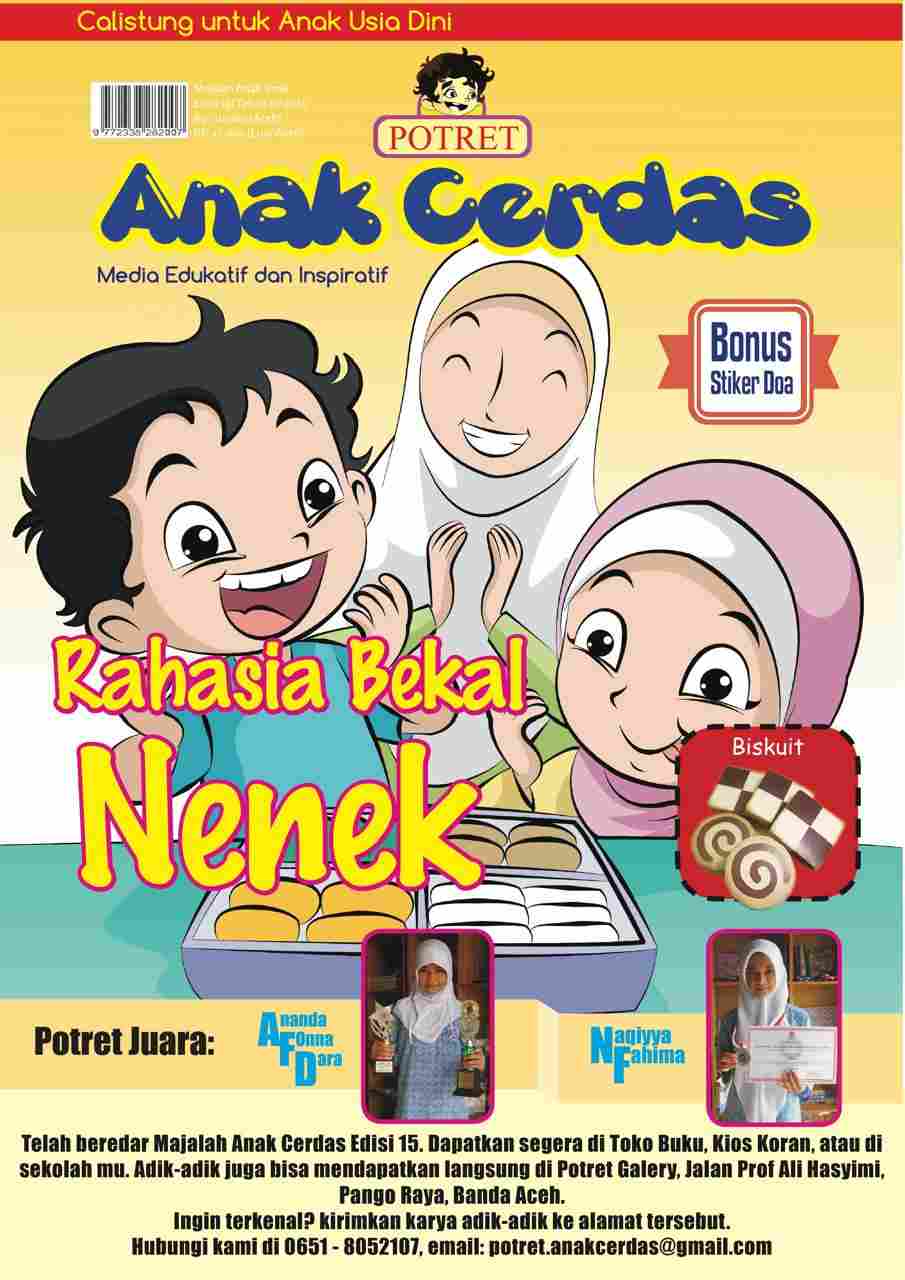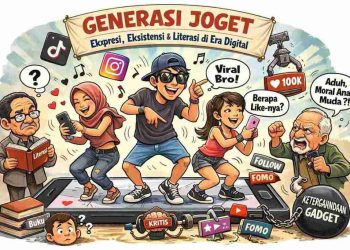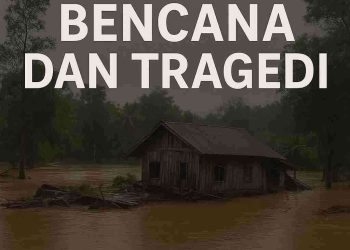Dengarkan Artikel
Oleh Dayan Abdurrahman
Reformasi 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Ia hadir sebagai respons terhadap otoritarianisme Orde Baru, dengan semangat menegakkan demokrasi substansial yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat. Namun, dalam dua dekade terakhir, politik Indonesia menunjukkan gejala regresif melalui maraknya politik dinasti, yakni pola kekuasaan yang diwariskan secara informal dalam lingkaran keluarga atau kekerabatan elite politik.
Fenomena ini tidak hanya mengancam idealisme demokrasi, tetapi juga memperlemah daya dorong negara dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Secara teoritis, demokrasi sebagai sistem pemerintahan seharusnya membuka ruang partisipasi yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara, terlepas dari latar belakang sosial, kekerabatan, atau kedekatan struktural dengan kekuasaan. Namun, politik dinasti justru melanggengkan eksklusivitas kekuasaan.
Dalam perspektif aliran sosial dan politik klasik seperti pluralisme dan struktural fungsionalisme, dinasti politik mencerminkan disfungsi sistem demokrasi. Ia mempersempit mobilitas politik vertikal dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Secara empiris, data dari berbagai pilkada menunjukkan bahwa politik dinasti tidak jarang berkorelasi dengan rendahnya kualitas kepemimpinan, penyalahgunaan anggaran, dan lemahnya akuntabilitas publik.
Fenomena politik dinasti tak dapat dilepaskan dari relasi antara partai politik (parpol) dan oligarki. Parpol yang seharusnya menjadi kendaraan artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, kerap kali menjadi instrumen akumulasi kuasa oleh elite keluarga atau kelompok tertentu. Proses seleksi kandidat yang tidak demokratis, mahalnya biaya politik, serta minimnya kaderisasi menjadi penyebab utama mengapa politik dinasti bertumbuh subur. Akibatnya, kepemimpinan nasional dan daerah tidak berdasarkan meritokrasi, melainkan berdasarkan loyalitas dan relasi darah. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan yang menjadi esensi demokrasi modern.
📚 Artikel Terkait
Dalam kerangka besar tujuan kemerdekaan, politik dinasti menjadi rintangan serius dalam pencapaian kemakmuran dan keadilan sosial. Kepemimpinan yang lahir dari sistem yang tidak adil cenderung menghasilkan kebijakan publik yang bias dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas. Ini berdampak langsung pada ketimpangan sosial, kemiskinan struktural, serta akses yang timpang terhadap pendidikan, layanan kesehatan, termasuk gizi masyarakat yang memadai. Ketika elite politik lebih fokus pada pelanggengan kekuasaan daripada pelayanan publik, maka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sekadar slogan kosong.
Lebih lanjut, stabilitas nasional bukan hanya persoalan militer dan keamanan semata, tetapi mencakup stabilitas sosial, budaya, serta kohesi antarkelompok masyarakat. Politik dinasti sering memicu ketegangan sosial, karena menciptakan persepsi ketidakadilan dan ketimpangan akses terhadap kekuasaan. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, hal ini dapat memicu konflik horizontal yang mengancam kesatuan bangsa. Bahkan dalam konteks seni dan budaya, kepemimpinan yang lahir dari politik dinasti sering tidak memiliki sensitivitas terhadap keragaman nilai lokal dan kearifan budaya, sehingga menurunkan daya saing identitas kebudayaan nasional di tengah globalisasi.
Agama sebagai salah satu pilar kehidupan masyarakat Indonesia juga tidak lepas dari imbas politik dinasti. Ketika kekuasaan diwariskan bukan karena kapabilitas, tetapi karena kedekatan struktural, maka nilai-nilai moral, etik, dan spiritualitas publik mudah dikompromikan. Politik dinasti membuka ruang pragmatisme dan transaksionalisme politik yang pada akhirnya mencederai nilai-nilai religius dalam tata kelola pemerintahan. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga keagamaan pun terseret dalam kontestasi politik yang bersifat dinastik, sehingga mengikis kepercayaan publik terhadap netralitas moral agama.
Dalam perspektif keilmuan multidisipliner, gejala politik dinasti tidak dapat dilihat secara parsial. Ia merupakan hasil interaksi kompleks antara struktur sosial, kelembagaan politik, perilaku elite, dan budaya politik masyarakat. Oleh karena itu, solusi terhadap permasalahan ini pun harus bersifat struktural dan kultural. Secara struktural, perlu ada revisi mendasar terhadap sistem rekrutmen politik, pembiayaan partai, serta pendidikan politik publik. Kelembagaan negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus diberdayakan secara independen untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan. Dari sisi budaya, masyarakat perlu didorong untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawasi proses demokrasi, tidak terjebak dalam politik identitas atau loyalitas sempit terhadap figur tertentu.
Dengan demikian, perdebatan mengenai politik dinasti bukan sekadar persoalan teknis atau prosedural dalam demokrasi, melainkan menyangkut kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi demokrasi tidak akan bermakna jika sistem kepemimpinan masih didominasi oleh kelompok-kelompok yang mengedepankan warisan kekuasaan, bukan gagasan dan kinerja. Untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan—yakni menciptakan kesejahteraan umum dan menghapus segala bentuk penjajahan dalam makna struktural dan simbolik—Indonesia memerlukan transformasi politik yang radikal: dari politik yang berbasis warisan, menuju politik yang berbasis kapasitas, etika, dan visi kebangsaan.
Penulis peminat isu sosial budaya dan politik
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini