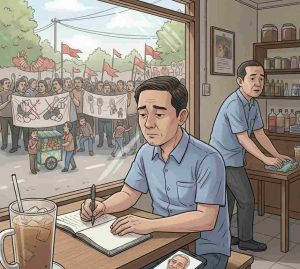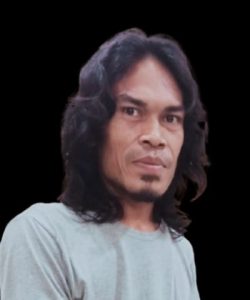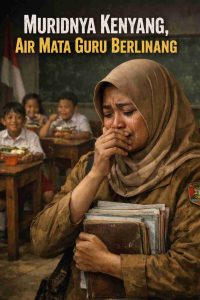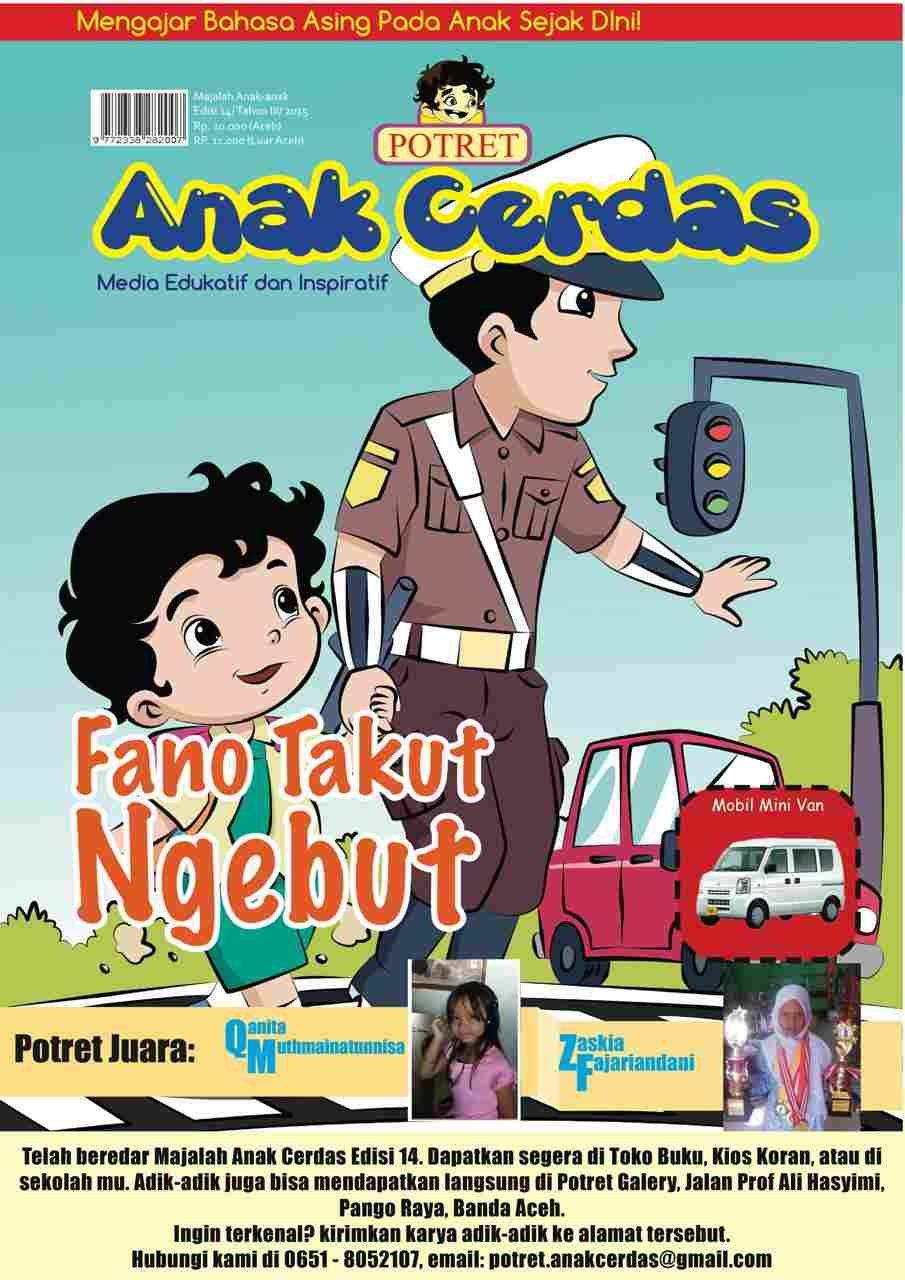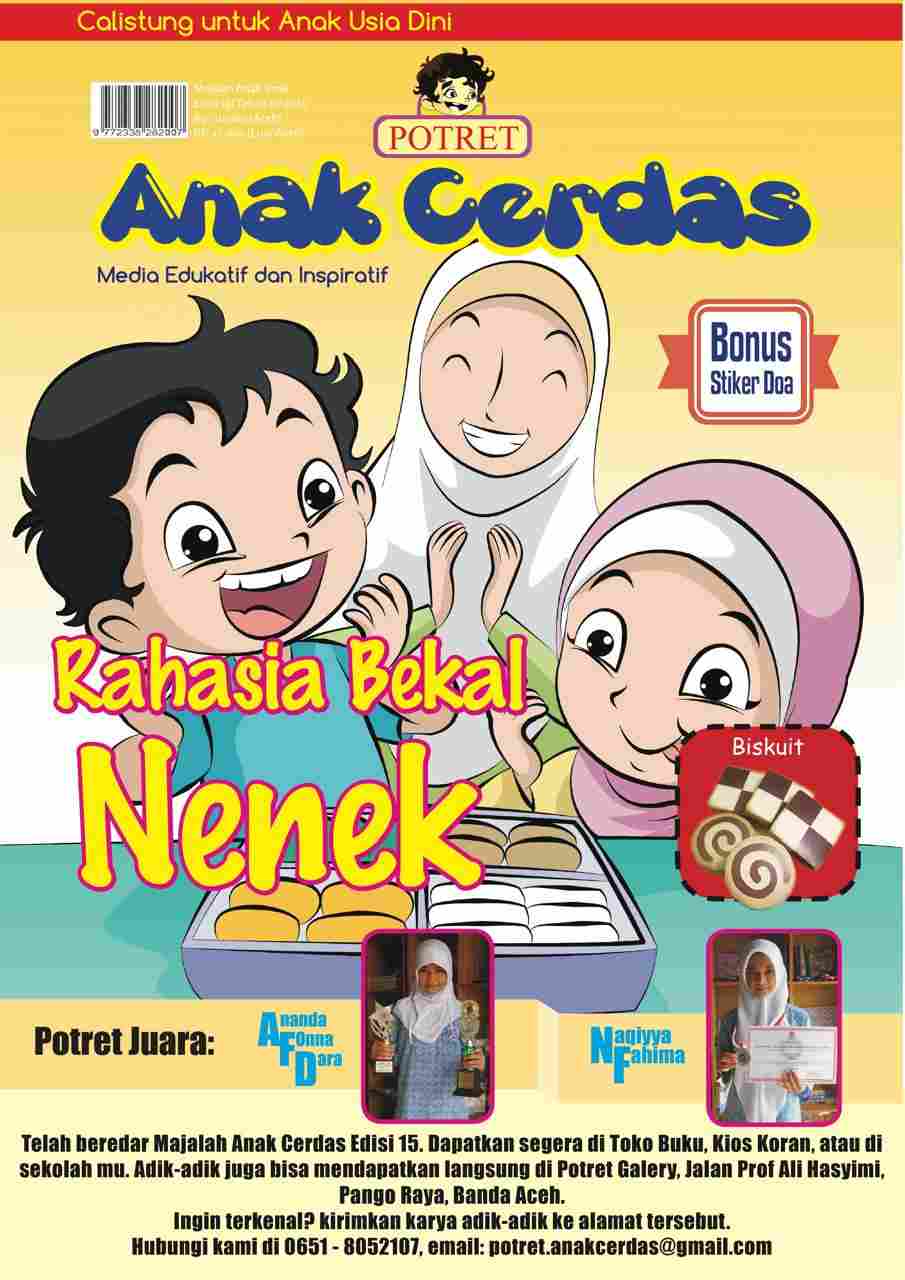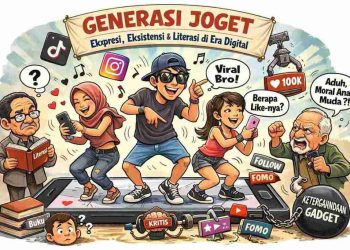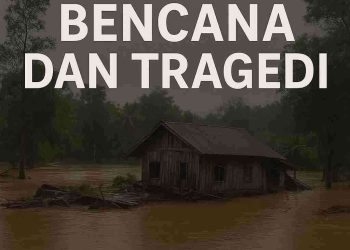Dengarkan Artikel
Oleh ReO Fiksiwan
Kadang, tidak menyebut Tuhan adalah cara paling halus untuk menghormati semua nama-Nya.” — Christopher Morrissey dalam Plato in Indonesia(Terjemahan 2022)
Di tengah panggung diplomasi global yang sering kali dibanjiri jargon teknokratis dan retorika steril, pidato Presiden Prabowo Subianto di Perserikatan Bangsa-Bangsa muncul sebagai anomali yang menggugah.
Ia tidak menyebut Tuhan, tapi justru menghadirkan semangat ketuhanan dalam bentuk yang paling universal: penghormatan terhadap martabat manusia.
Dalam konteks pembacaan semiotik terhadap pidato Presiden Prabowo yang, menurut Morrissey, mengandung spiritualitas politik tanpa harus menyebutkan simbol religius secara eksplisit.
Ia menafsirkan bahwa dalam masyarakat majemuk, keheningan teologis bisa menjadi bentuk tertinggi dari adab politik, terutama dalam forum internasional seperti PBB.
Dalam era digital yang sarat progresfobia dan pasca-kebenaran abad ke-21, pidato itu bukan sekadar pernyataan politik, melainkan sebuah semiotik peradaban yang menolak tunduk pada algoritma kebisingan.
Samuel Huntington pernah menyatakan dalam The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order(1996) bahwa benturan peradaban akan menjadi konflik utama di dunia pasca-Perang Dingin. Tapi Prabowo, dalam pidatonya, tidak memilih benturan. Ia memilih jembatan.
Ia tidak bicara tentang superioritas budaya, tapi tentang kesetaraan martabat. Ia tidak menyerukan perang ideologi, tapi menyuarakan perdamaian yang berakar pada adab politik.
Di saat banyak pemimpin dunia sibuk membela kepentingan nasional dengan nada eksklusif, Prabowo justru menyisipkan kalimat yang menyentuh: “Kita semua adalah bagian dari keluarga besar umat manusia.”
Sebuah kalimat yang sederhana, tapi mengandung resonansi humanisme yang dalam.
Yuval Noah Harari dalam 21 Lessons for the 21st Century (2018) mengingatkan bahwa tantangan terbesar umat manusia bukan lagi perang nuklir, melainkan kehilangan makna dan kebenaran dalam era informasi.
Pidato Prabowo, dalam konteks ini, menjadi upaya untuk mengembalikan makna politik internasional sebagai ruang etis, bukan sekadar arena kalkulasi.
📚 Artikel Terkait
Ia tidak bicara tentang Tuhan, tapi ia bicara tentang nilai yang seharusnya menjadi cerminan dari spiritualitas politik: keadilan, solidaritas, dan keberanian untuk berbeda tanpa saling meniadakan.
Steven Pinker dalam Enlightenment Now (2018) menulis bahwa kemajuan manusia bergantung pada akal, ilmu, dan humanisme.
Tapi di era ketika politik domestik justru dirundung oleh anti-kemanusiaan yang diwarisi dari rezim sebelumnya, pidato Prabowo menjadi paradoks yang menyentuh.
Di luar negeri, ia bicara tentang perdamaian, tapi di dalam negeri, rakyat masih bergulat dengan ketimpangan, kekerasan struktural, dan warisan oligarki yang belum dibongkar.
Dengan demikian, pidato itu bukan hanya harus diapresiasi, tapi juga diuji: apakah semiotik humanisme itu akan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat, atau hanya menjadi etalase diplomatik yang indah tapi hampa?
John Green dalam The Anthropocene Reviewed (2021) menulis tentang bagaimana manusia menilai dunia di tenhjagah kerusakan yang mereka ciptakan sendiri.
Pidato Prabowo, dalam lanskap ini, adalah upaya untuk menilai ulang politik sebagai ruang harapan, bukan sekadar instrumen kekuasaan. Ia tidak menyebut Tuhan, tapi ia menyebut kemanusiaan.
Dan mungkin, di zaman ketika nama Tuhan sering kali dipakai untuk membenarkan kekerasan, ketidakhadiran Tuhan dalam pidato itu justru menjadi bentuk tertinggi dari spiritualitas politik.
Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi oleh identitas, algoritma, dan ketakutan, pidato Prabowo di PBB adalah pengingat bahwa politik internasional masih bisa menjadi ruang untuk menyuarakan adab, bukan sekadar kepentingan. Tapi adab itu harus diuji di dalam negeri.
Karena humanisme universal tidak akan berarti jika rakyat sendiri masih diperlakukan sebagai angka, bukan manusia.
Maka, tak ada Tuhan dalam pidato itu bukanlah kekurangan, tapi justru keberanian untuk menyuarakan nilai-nilai ketuhanan tanpa menyebut nama-Nya.
Sebuah langkah kecil menuju politik yang lebih dewasa, lebih reflektif, dan lebih manusiawi. Jika ia konsisten. Jika…
#coversongs: „We Are the Champions” adalah lagu legendaris dari band rock asal Inggris, Queen, yang dirilis pada 7 Oktober 1977 sebagai bagian dari album News of the World.
Lagu ini ditulis oleh vokalis utama Queen, Freddie Mercury, dan sejak saat itu menjadi anthem kemenangan yang ikonik di seluruh dunia.
“We Are the Champions” bukan sekadar lagu kemenangan. Di balik chorus yang megah dan melodi yang menggugah, lagu ini menyimpan pesan tentang ketekunan, penderitaan, dan pembuktian diri.
Mercury menulisnya sebagai refleksi atas perjuangan panjang—baik secara pribadi maupun kolektif—untuk mencapai pengakuan dan keberhasilan.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini